Bila tidak ada persamaan pada agama-agama, kita tidak akan menyebutnya dengan nama yang sama ‘agama’. Bila tidak ada perbedaan diantaranya, kita pun tidak akan menyebutnya dengan kata majemuk ‘agama-agama’. Begitu kira-kira menurut mistikus Islam, Fritchof Schuon dalam karya terkenalnya The Trancendent Unity of Religions dalam mencari titik temu antar agama-agama.
Sederhananya begini, setiap kita menyebutkan agama kepada setiap agama-agama yang berbeda nama, secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menyadari tentang keberadaan agama lain. Secara tidak langsung pula, kita telah meletakkan semua agama pada posisinya sebagai agama, meskipun dalam bentuk esensi belum tentu sama.
Disinilah tujuan agama, Islam misalnya, sebagai ad-dien yang diturunkan untuk menjadi rahmatan lil-‘alamin harus dipahami secara tuntas. Kehadiran Islam sebagai rahmat seluruh alam ke dunia dimaksudkan untuk membangun sebuah peradaban kemanusiaan yang sesuai dengan fitrah manusia. Peradaban yang dimaksud adalah upaya-upaya yang berorientasi pada keyakinan adanya kekuasaan Tuhan yang esa, keadilan, kesamaan manusia dan kebebasan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai maupun tradisi keilmuan. Peradaban inilah nantinya menjadi titik temu antar agama-agama yang berbeda namanya tadi.
Goenawan Mohammad dalam sebuah tulisan di bawah judul “Piyadasi” menarasikan tentang sebuah monument setinggi 15 meter yang berisi 14 titah Baginda Raja Devanampiyadasi.
Titah yang ke-7 begitu mempesona Pendiri Komunitas Utan Kayu ini. Titah ke-7 itu menjelaskan bahwa semua agama boleh hadir dimanapun karena setiap agama mempunyai tujuan yang sama, yakni pengendalian diri (nafsu) dan pemurnian hati.
Jauh merentang ribuan mil dari Kerajaan tempat Devanampiyadasi bertahta, terdapat sebuah Kerajaan Agung Nusantara, bernama Majapahit. Kerajaan yang dipuncak keemasannya sanggup membangun relasi yang indah antara Hindu dan Buddha. Pemeluk Hindu dan Budhha saling hidup rukun tanpa saling sengketa. Bahkan, ketika Islam masuk pun, diterima dengan suka cita oleh penduduk Majapahit kala itu. Mengapa bisa demikian?
Dalam kitab Sutasoma terpatri sesanti agung yang maknanya sama dengan titah Raja Piyadasi. Sesanti itu berbunyi; “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Mangrwa”. Berbeda tapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua, demikian arti sesanti itu.
Majapahit dan Raja Piyadasi mempunyai resonansi yang sama dengan Rasullullah Muhammad SAW di Madinah. Melalui piyagam Madinah, Rasullullah Muhammad SAW meneguhkan bahwa Islam, Kristen, dan Yahudi harus hidup saling bekerja sama untuk membangun masyarakat yang damai. Inilah mozaik ajaran untuk beragama secara berkebudayaan, bukan beragama Sontoloyo. Jika anda Kristen, berKristenlah sebagaimana Kristus mengajarkan, yang menabur kasih kepada siapapun. Jika anda Buddha, ikutilah ajaran Shidarta dengan sepenuh hati. Jika anda Hindu, pegang teguh Tri Hitta Kerana. Jika anda Konghucu, simak terus ajaran konfusius.
Misalnya anggapan Muslim tentang agamanya, bahwa Islam sebagai cara hidup memiliki keunggulan atas cara-cara hidup yang lain, sebenarnya tidak salah. Setiap orang dan semua umat beragama tentu menganggap sistemnya sendiri yang benar. Karena itu perbedaan cara hidup adalah sesuatu yang wajar. Ini termasuk dalam apa yang dimaksud oleh al-Qur’an dalam Surat al-Hujurat (49):13; “Dan telah Ku buat kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, agar kalian saling mengenal” (wa ja’alnakum syu’uban waqabaila li ta’arafi).
Demikian pula agama-agama adat di Indonesia, semuanya mengajak untuk mengendalikan diri dan pembersihan hati. Dan jika anda Muslim, sebagai mayoritas, jadilah Muslim yang mencintai kedamaian, muslim yang menebar salam ke seluruh umat manusia.
Mari kita merayakan Bhinneka Tunggak Ika Tan Hana Mangrwa. Beragama dengan cara menyapa agama lain, bukan menaruh curiga, Pancasila menyeru kita untuk tidak melakukan penghakiman terhadap seseorang atau kelompok –pun demikian dengan Islam bahkan agama apapun mengajarkan kita untuk hidup rukun saling menghormati.
Keragaman bangsa Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak abad ke-12 sampai 13 Masehi. Dalam sejarahnya, sikap pluralis di Indonesia sudah terbangun jauh sebelum bangsa kita merdeka. Kerajaan Sriwijaya misalnya, Kerajaan yang berada di Sumatera Selatan yang kemudian menyerbu Pulau Jawa pada abad ke-8 Masehi melalui Pekalongan yang kemudian melanjutkan perjalanan ke pedalaman Jawa Tengah dan akhirnya bertemu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga yang mayoritas beragama Hindu (sekarang sekitar daerah Kabupaten Wonosobo) itu tidak mendapat paksaan dari Kerajaan Sriwijaya untuk berpindah agama dari Hindu menjadi Buddha. Para orang-orang Sriwijaya itu kemudian tetap melanjutkan perjalanannya ke Selatan, dan di daerah Magelang sekitar Muntilan sekarang mereka mendirikan Candi Borobudur.
Mereka yang tidak ikut turut mendirikan Candi Borobudur, meneruskan perjalanan ke kawasan Yogyakarta. Di tempat itu mereka mendirikan Kerajaan Kalingga yang beragama Buddha pada abad ke-8 Masehi. Pada abad tersebut, berdirilah Candi Roro Jonggrang di Prambanan. Baik Kalingga Hindu maupun Kalingga Buddha sama-sama marah atas berdirinya Candi tersebut. Akibat penentangan itu Candi Roro Jonggrang di tinggalkan oleh penduduknya yang beragama Hindhu-Buddha ke Kediri di Jawa Timur di bawah kepemimpinan Prabu Darmawangsa. Di Kediri, mereka mendirikan Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi Kerajaan Daha, dengan Raja yang sangat terkenal bernama Prabu Airlangga. Dua abad kemudian, mereka berpindah ke kawasan Singasari dengan tetap memeluk agama Hindu-Buddha.
Di Singasari, kurang lebih 10 kilometer sebelah utara kota Malang sekarang, pada abad ke-11 Masehi mereka mendirikan Kerajaan Hindu-Buddha dengan Rajanya yang terkenal Tunggulametung dan Ken Arok. Dia inilah yang memperistri Ken Dedes, yang dianggap memiliki kesaktian sendiri. Pada abad ke-13 Masehi, Prabu Kertanegara dari Singasari harus merelakan menantunya mendirikan Kerajaan baru di Terik, pinggiran sungai Brantas dekat Krian. Kerajaan inilah yang kemudian menjadi Kerajaan Majapahit yang didirikan menantu Prabu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya.
Menurut dugaan penulis, Raden Wijaya adalah seorang Tionghoa angkatan Laut Tiongkok, yang waktu itu hampir seluruhnya anggota tarekat. Di bawah perlindungan orang-orang Muslim Tiongkok yang menjadi anggota tarekat itu, Majapahit lalu tumbuh sebagai negara multiagama dan etnis.
Walaupun beragama Islam, kaum santri yang menjadikan nama tempat berdirinya Kerajaan Majapahit di Terik, yang berarti tarikat, tetap menghargai multi agama itu. Hal inilah yang kemudian mendasari Mpu Tantular di abad ke-15 Masehi, merumuskan kerajaan Majapahit memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang kemudian hari, di tahun 1945, medasari Bung Karno untuk merumuskan Pancasila sebagai sikap hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, sejarah modern Indonesia juga diwarnai oleh gagasan keragaman, pluralistik tersebut.
Sejarah diatas tersebut menunjukkan bahwa kerununan, toleransi dalam kehidupan kita yang beragam terjadi jauh sebelum Islam hadir di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Maka, peradaban kerukunan antar agama yang sudah kokoh sedari dulu tidak seharusnya kita robohkan, apalagi kita tinggalkan.

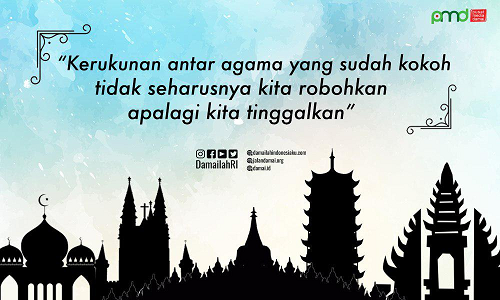


![download[5]](https://jalandamai.org/wp-content/uploads/2016/09/download-here.png)