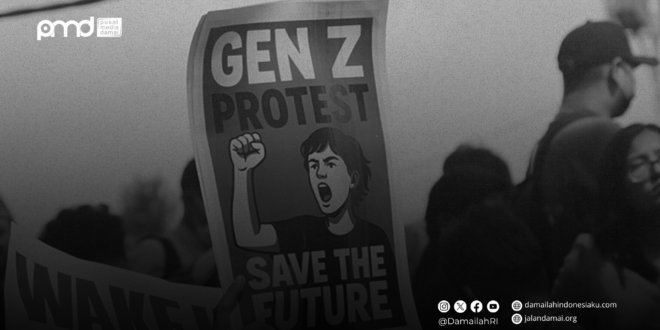Aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia di akhir Agustus lalu menginspirasi lahirnya gerakan serupa di Nepal. Generasi Z Nepal berdemonstrasi memprotes ketidakadilan, korupsi, dan gaya hidup hedonis anak pejabat di tengah langkanya lapangan pekerjaan.
Massa membakar rumah Perdana Menteri. Istri sang Perdana Menteri pun tewas. Rumah para pejabat pun tidak luput menjadi sasaran amuk massa. Video kerusuhan Nepal itu berseliweran di media sosial sepekan terakhir.
Dalam beberapa tahun belakangan, aktivisme generasi Z di ranah sosial dan politik memang menunjukkan gejala kebangkitannya. Gen Z yang kerap diidentikkan sebagai generasi strawberry atau generasi TikTok yang lemah dan apatis nyatanya berhasil membalikkan labelisasi tersebut. Mereka menunjukkan kepedulian pada isu-isu sosial politik seperti kerusakan alam, bobroknya demokrasi, genosida Gaza, dan sebagainya.
Dalam konteks Indonesia, aktivisme Gen Z cukup berkontribusi pada dinamika sosial politik nasional. Sebagai sebuah gerakan sosial-politik, aktivisme generasi Z ini kerap berhadapan dengan dilema. Di satu sisi, aktivisme generasi Z merupakan bentuk empati terhadap ketidakadilan di bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Namun, di sisi lain aktivisme generasi Z ini kerap pula ditunggangi oleh narasi kebencian dan kekerasan.
Munculnya kerusuhan pada demonstrasi akhir Agustus lalu membuktikan bahwa aktivisme generasi Z itu masih terjebak pada narasi kebencian dan kekerasan. Setidaknya ada tiga perspektif atau sudut pandang untuk memahami mengapa aktivisme gen Z ini masih kerap terjebak pada narasi kebencian bahkan kekerasan.
Pertama, aktivisme gen Z masih kerap terjebak pada model gerakan slacktivism, yakni gerakan yang berbasis di ranah digital namun tidak melakukan aksi konkret di dunia nyata. Generasi Z aktif memperbincangkan isu sosial politik bahkan kemanusiaan di dunia maya, namun tidak melakukan aksi subtansial di dunia nyata. Alhasil, mereka kerap hanya berisik dan gaduh di medsos, namun minim aksi di lapangan.
Kegaduhan di medsos inilah yang rawan menjadi ruang bagi tumbuhnya narasi kebencian dan kekerasan. Banjir opini di ruang publik digital itu kerap dieksploitasi oleh kelompok tertentu untuk mengadu-domba masyarakat dan pemerintahnya atau memecah-belah antar-sesama masyarakat itu sendiri.
Kedua, aktivisme generasi Z cenderung tidak memiliki pengalaman alias amatir. Keterbatasan pengalmn ini membuat aktivisme generasi Z kerap gagal mengkoordinasikan gerakan. Mereka cenderung impulsif dalam menggeloran perlawanan. Alhasil, gelombang perlawanan itu kerap minim gagasan atau argumen, yang membuat sejumlah pihak dengan mudah membajak agenda gerakan tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Demonstrasi itu tidak secara spesifik menyampaikan apa yang dituntut dari pemerintah. Aksi demo itu lebih merupakan ekspresi kemarahan. Tidak ada tuntutan yang jelas sampai akhirnya banyak provokator yang mengeksploitasi aksi demonstrasi tersebut.
Ketiga, kondisi psikologis dan mental generasi Z yang kurang stabil dan reaksioner kerap membuat gerakan mereka cenderung mudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Instabilitas mental generasi Z dan sikap reaksioner mereka atas isu-isu strategis kerap membuat arah gerakan menjadi ambigu. Di satu sisi mereka menyuarakan empati pada ketidakadilan. Namun, di sisi lain mereka kerap permisif pada tindakan kekerasan.
Sebagai ceruk demografi paling besar dalam lanskap populasi di Indonesia, generasi Z menempati posisi strategis. Baik dalam isu sosial, politik, agama, budaya, dan sebagainya. Opini generasi Z terutama di media sosial berpotensi menjadi narasi utama perbincangan di tengah publik. Aktivisme gen Z dengan demikian akan sangat menentukan arah bangsa dan negara ke depan.
Maka, kita perlu merancang aktivisme generasi yang konstruktif, bukan destruktif. Tugas generasi muda hari ini adalah mendesain sebuah gerakan sosial-politik yang murni berempati pada ketidakadilan, tanpa menyisakan celah untuk narasi kebencian dan kekerasan. Apa yang terjadi di Nepal patut menjadi pelajaran.
Dalam konteks Indonesia, anak muda perlu merancang aktivisme sosial politik yang independen, solutif, dan nir-kekerasan. Independen dalam artian bahwa aktivisme gen Z idealnya steril dari kepentingan berbau partisan, sektarian, apalagi sentimen ideologi keagamaan. Aktivisme gen Z idealnya murni mengusung aspirasi publik tentang terciptanya pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas.
Kritis dalam artian bahwa aktivisme gen Z idealnya mampu menawarkan solusi atas berbagai problem kebangsaan dan kenegaraan. Aktivisme gen Z tidak boleh jatuh ke dalam model gerakan yang hanya mengumbar kritisisme namun lupa menghadirkan tawaran solusi. Aktivisme gen Z tidak boleh terjebak pada idiom klasik, yakni NATO (no action talk only) alias hanya berwacana namun miskin aksi nyata.
Terakhir, nir-kekerasan dalam artian bahwa aktivisme gen Z harus steril dari narasi kebencian dan kekerasan. Gerakan sosial-politik yang dimotori gen Z idealnya harus bertumpu pada prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Itu artinya, gerakan protes yang dimotori gen Z harus mengedepankan akal sehat dan tidak melampaui batas norma sosial, apalagi sampai melanggar hukum.