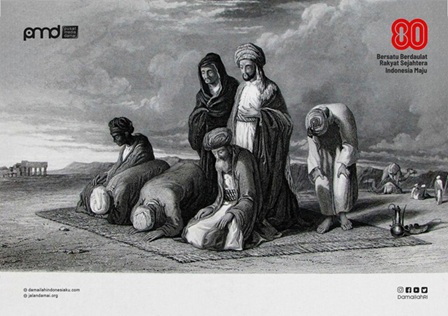Tak ada yang dapat menyangkal bahwa kecerdasan buatan, atau AI, telah menjadi salah satu anugerah paling transformatif di abad ini. Ia hadir sebagai manifestasi kecerdasan manusia yang meluas, menawarkan efisiensi, dan membuka pintu bagi kemajuan di berbagai bidang. Namun, di tengah gemuruh perayaan atas kemajuan ini, kita acap kali lupa bahwa setiap anugerah besar selalu datang dengan ujiannya sendiri. Seperti sebilah pedang yang tajam, AI memiliki dua mata: satu untuk membelah jalan menuju kemudahan, satu lagi berpotensi melukai jika kita tidak berhati-hati.
Bagi generasi muda, yang lahir dan tumbuh di tengah ruang digital tanpa batas, daya pikat AI sungguh luar biasa. Ia ibarat teman yang selalu ada, mampu memberikan jawaban instan, dan menghadirkan dunia hiburan tanpa henti. Namun, di balik pesona itu, tersembunyi sebuah ancaman yang jauh lebih subtil dan berbahaya daripada yang bisa kita bayangkan: tergerusnya nalar kritis.
Dalam tradisi intelektual Islam, para ulama telah lama memperingatkan kita tentang pentingnya al-`aql (akal). Akal bukanlah sekadar alat untuk berpikir, melainkan sebuah instrumen ilahiah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Fungsinya adalah untuk memilah al-haqq (kebenaran) dari al-bathil (kebatilan), membedakan al-manfa’ah (manfaat) dari al-madharat (kerugian). Bahkan Al-Qur’an secara berulang kali menyeru manusia untuk menggunakan akal, merenung, dan tidak sekadar ikut-ikutan.
Namun, bagaimana jika akal kita sendiri, secara perlahan, dibajak oleh algoritma? Inilah salah satu bahaya terbesar AI.
Pertama, AI berpotensi mengikis otonomi manusia. Kita menyaksikan bagaimana AI memantau, memetakan, dan pada akhirnya mengarahkan kebiasaan digital kita. Fenomena filter bubble dan echo chamber adalah buktinya. Generasi muda menjadi terkurung dalam gelembung informasi yang seragam, hanya mendengar suara-suara yang sama, dan kehilangan kemampuan untuk berdialog dengan perbedaan. Hal ini kontradiktif dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang sejatinya tumbuh dalam dialektika, bukan dalam keseragaman yang steril.
Kedua, AI berisiko menciptakan homogenisasi budaya. Algoritma yang didominasi oleh perusahaan teknologi global cenderung memprioritaskan konten-konten seragam. Lambat laun, aksara Nusantara, sastra klasik, atau lagu-lagu daerah kita mulai tersisih, tenggelam di antara lautan konten global yang masif. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa kolonialisme, di mana penjajah tidak hanya merampas tanah, tetapi juga membentuk selera dan cara berpikir masyarakat? Bedanya, kini ‘kolonialisme digital’ ini hadir dalam bentuk yang lebih halus, mengubah selera dan perspektif generasi muda tanpa mereka sadari.
Dalam perspektif geopolitik, AI bukanlah sekadar alat, melainkan senjata. Negara-negara adidaya berlomba-lomba menguasai teknologi ini, menggunakannya untuk tujuan militer, ekonomi, dan bahkan pengawasan sosial. Penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mengawasi warga adalah contoh nyata betapa AI dapat menjadi alat kontrol yang menakutkan. Jika generasi muda tidak memahami dimensi ini, mereka hanya akan menjadi pion dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar.
Prinsip Islam la dharar wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) menjadi relevan di sini. Prinsip ini menuntut kita untuk bersikap kritis terhadap penggunaan AI, terutama jika ia berpotensi memanipulasi opini publik, melanggar privasi, atau bahkan digunakan dalam peperangan yang tidak adil.
Bagaimana kita dapat membekali generasi muda untuk menghadapi tantangan ini? Jawabannya ada pada pendidikan. Kita harus mengajarkan literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga filosofis dan etis. Dalam tradisi pesantren, ada konsep tazkiyatun nafs—penyucian jiwa. Konsep ini bisa kita perluas menjadi penyucian cara pandang terhadap teknologi, melatih generasi muda untuk bertanya: apakah AI mendekatkan kita pada nilai-nilai kemanusiaan, atau justru menjauhkan kita dari jati diri?
Tradisi pendidikan Nusantara selalu menekankan keseimbangan antara akal, rasa, dan iman. Pendekatan ini akan mencegah generasi muda mengagungkan AI secara berlebihan, seakan-akan ia adalah ‘tuhan baru’ yang serba tahu. Dengan menyelaraskan ketiganya, mereka akan menyadari bahwa teknologi hanyalah bagian dari jalan, bukan tujuan akhir.
Pada akhirnya, AI adalah sebuah anugerah, tetapi ia juga merupakan ujian. Generasi muda Indonesia, dengan segala potensinya, harus dipandu untuk memahami sisi gelap teknologi ini agar tidak terjerumus menjadi budak algoritma. Kesadaran kritis perlu dirawat melalui pendidikan yang mengakar pada filsafat Islam, kebudayaan Nusantara, dan analisis politik global.
Pepatah Arab mengatakan, al-insanu ibnu ‘asrih (manusia adalah anak zamannya). Tetapi menjadi anak zaman tidak berarti hanyut dalam arusnya. Justru, dengan nalar yang tajam dan kesadaran mendalam, generasi muda harus tampil sebagai penentu arah, bukan sekadar pengikut. Maukah kita merawat kesadaran ini agar mereka menjadi tuan atas teknologi, bukan sebaliknya?