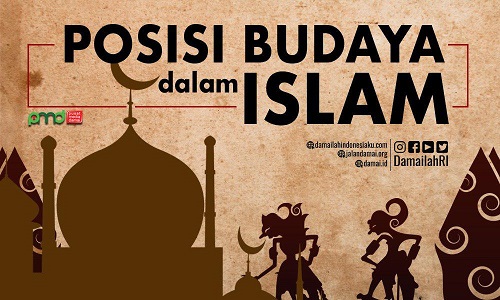Ibu Indonesia, puisi yang dilantunkan Sukmawati Soekarnoputri, pada 29 Tahun Anne Avantie Berkarya, Kamis (29/3/2018), menuai protes keras dari berbagai kalangan. Laporan demi laporan ke pihak berwajib terus bermunculan. Ketersinggungan rasa keberagamaan, menjadi alasannya. Sukmawatipun buru-buru minta maaf, melalui berbagai media. Tokoh-tokoh penting disambanginya, sebagai bentuk keseriusan penyesalannya.
Bagian mana dari puisinya, yang menyinggung rasa keberagamaan sebagian orang itu? Jika diperhatikan seksama, setidaknya ada dua point utama puisinya yang dinilai tidak peka terhadap rasa keagamaan atau kepercayaan/keyakinan pihak lain. Pertama, “Aku tak tahu Syariat Islam // Yang kutahu sari konde Ibu Indonesia sangatlah indah // Lebih cantik dari cadar dirimu.”
Ungkapan ini dinilai menyinggung kepercayaan/keyakinan kalangan muslim ber-niqab (cadar). Selama ini, niqab memang dipandang negative oleh kalangan yang tidak menyetujuinya. Berbagai kritik terlontar karenanya, termasuk melalui puisi yang dikumandangkan oleh puteri Bung Karno itu. Penyandingan dan pembandingan dengan Sari Konde, dinilai tidak tepat dan gegabah. Bahkan cenderung melecehkan “sakralitas” cadar yang dinilai oleh yang meyakininya sebagai bagian dari Syariah Islam.
Kedua, “Aku tak tahu syariat Islam // Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok // Lebih merdu dari alunan azanmu.” Ungkapan ini juga dinilai menyakitkan kalangan muslim. Jika yang pertama hanya “menyerang” kelompok muslim bercadar, sangat terbatas, maka ungkapan kedua dinilai menyerang keyakinan seluruh kaum muslim. Azan diyakini sakral oleh kaum muslim, karena sebagai sarana pembukan pelaksanaan ritual shalat. Merendahkan azan sama halnya merendahkan bangunan keyakinan kaum muslim.
Sebagai manusia yang bebas, hak Sukmawati untuk menyampaikan isi hatinya, termasuk melalui ungkapan atau diksi yang paling disukainya. Juga haknya untuk mengritik perilaku keagamaan pihak lain. Namun tentu saja, semua itu harus dengan mempertimbangkan perasaan keagamaan pihak lain. Niat baik yang disampaikan dengan mengesampingkan perasaan pihak lain, menjadi tidak baik dan bahkan buruk.
Santri-santri di pesantren tradisional, hafal di luar kepala kata hikmah yang patut direnungkan: li kulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Di setiap situasi ada ucapan yang patut dan tidak patut disampaikan. Tidak semua ucapan harus disampaikan dalam setiap situasi. Tidak setiap kritikan mesti disampaikan secara terbuka dan menjadi tontonan khalayak, tanpa mempertimbangkan perasaan pihak lain yang menjadi sasaran kritiknya. Apalagi di tengah situasi kebangsaan yang sedikit retak dan goyah ini, kritikan yang tidak situasional bisa menjadi bahan bakar penyulut perpecahan. Dalam konteks ini, pembaca puisi yang memaksakan kritiknya justru terlihat kurang arif bijaksana. Dan atas tindakannya, hak orang yang tersinggung juga untuk mempersoalkannya, hatta ke kepolisian.
Namun demikian, terlepas pro kontra penyikapan Puisi Ibu Indonesia itu, semestinya semua hal bisa direspon dengan kepala dingin dan hati tenang. Bangsa besar yang penuh keramahan ini tidak boleh terjebak pada penghakiman yang berdampak pada runtuhnya kebersamaan bangunan rumah besar Indonesia. Semua ada mekanisme formalnya, yang mesti ditempuh sesuai alur prosedurnya.
Pertanyaan yang penting dilontarkan: bagaimana sesungguhnya Islam memosisikan budaya lokal? Apakah konsen Islam memberangus, mempertahankan atau memberangus sebagian dan mempertahankan sebagian budaya lokal? Jawabannya tentu saja sangat beragam.
Dikatakan Yusuf al-Qardhawi, ada dua hal penting yang semestinya dipahami terkait seluruh gugusan ajaran Islam: sasaran dan sarana. Baginya, yang terpenting dari ajaran Islam adalah sasaran atau substansi, bukan sarana. Sasaran itu universal dan sifatnya langgeng. Sedang sarana itu lokal dan sifatnya kondisional. Sasaran itu tidak berubah, sedang sarana itu berubah sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.
Dalam berpakaian misalnya, sasaran yang dituju oleh Islam adalah menutup aurat. Sedang sarananya adalah pakaian. Menutup aurat, sebagai sasaran demi melindungi bagian-bagian tubuh yang berpotensi menimbulkan bahaya/rangsangan, berlaku universal dan langgeng, kendati batasannya bisa debatable. Banyak pandanga fikih yang beragam tentangnya.
Untuk menutupinya, dibutuhkan sarana pakaian, yang bentuk dan modelnya sangat tergantung budaya lokal. Untuk tujuan yang sama, menutup aurat, pakaian bisa berbeda-beda bentuk dan modelnya sesuai kondisi geografis, lingkungan sosial dan kebiasaan masyarakat setempat. Tidak mesti pakaian di daerah tertentu, diterapkan secara leterlek untuk daerah lain. Belum tentu sesuai dan cocok. Perbedaan kondisi meniscayakan perbedaan sarana.
Yang terpenting dari menutup aurat, adalah karakter pakaian yang digunakan: tidak tembus pandang, tidak menunjukkan lekuk tubuh, dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Jika ketentuan ini sudah terjamin, maka apapun bentuk pakaian yang dikenakan, sudah dinilai sesuai dan berarti tidak bertentangan dengan syariah Islam. Pakaian khas wanita muslimah Indonesia, gamis disertai kerudung (khimar) umpamanya, jika telah memenuhi kreteria tutup aurat, maka sesuai syariah Islam. Kebaya khas Jawa atau Sunda, jika telah memenuhi kreteria tutup aurat, juga sudah cukup.
Dan bagi yang lebih meyakini cadar sebagai sarana menutup aurat, dengan balutan baju kurung yang besar menutupi sekujur tubuh, karena dinilai lebih sempurna, juga silahkan saja. Yang terpenting dipahami, baik kebaya, kerudung maupun cadar, adalah semata sarana yang sifatnya bisa berubah dan bukan sasaran yang sifatnya tetap atau langgeng. Menjadi tidak bijaksana jika kita semua sibuk berdebat, hingga “berdarah-darah”, perihal sarana dan justru mengabaikan sasaran.
Hormatilah mereka yang tidak mengenakan cadar, sebagaimana hormatilah mereka yang mengenakan cadar. Dengan catatan, mereka saling hidup berdampingan dengan tenteram dan saling membuka diri satu sama lain, sebagai satu kesatuan bangsa yang besar ini. Sebab, baik kebaya maupun cadar, keduanya sama-sama produk budaya lokal, bukan produk agama. Bahkan cadar tidak hanya dikenakan kaum muslim. Sebagian Yahudi dan Nashrani juga mengenakanya.
Penelitian Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, beberapa tahun silam yang berjudul Antropologi Jilbab, kiranya menunjukkan dengan baik sisi budaya cadar itu. Melalui buku berjudul Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer (Lentera Hati: 2004), pakar tafsir dunia, M. Quraish Shihab, melakukan kajian sangat baik dan mendalam. Kesimpulannya, jilbab atau cadar itu pakaian budaya. Bahkan Mahmud Hamdi Zaqzouq menulis buku yang lebih tegas lagi tentangnya: al-Niqab ‘Adah laisa ‘Ibadah: al-Ra’y al-Syar’i fi al-Niqab bi Aqlam Kibar al-‘Ulama (Mesir: 2008). Kiranya kesimpulan yang didapat tak jauh berbeda dari dua kesimpulan sebelumnya.
Apa maknanya? Posisi cadar masih diperdebatkan oleh kalangan ulama. Tidak bisa dimutlakkan oleh siapapun, karena bukan consensus ulama atau ijma’. Cadar tak ubahnya pakaian lokal, yang difungsikan sebagai penutup aurat. Kerudung atau kebaya khas Jawa/Sunda, atau pakaian adat lain di negeri ini, juga memiliki posisi yang sama dengan cadar: sarana untuk menggapai sasaran menutup aurat.
Di atas semua itu, tentu penempatan pakaian sesuai situasi dan kondisi penting dipahami. Pakaian untuk shalat, jangan disamakan dengan pakaian untuk ke sawah, kendati sama-sama menutup aurat. Bukan tidak boleh, namun tidak elok. Di sinilah Islam begitu bijaksana memosisikan budaya lokal. Tidak serta-merta menafikannya begitu saja. Inilah jalan dakwah Wali Songo yang luwes dan kontekstual, yang banyak diterima oleh bangsa ini. Cara dakwah yang memadukan Islam dan budaya inilah warisan mahal bangsa ini sesungguhnya, yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslim urban.