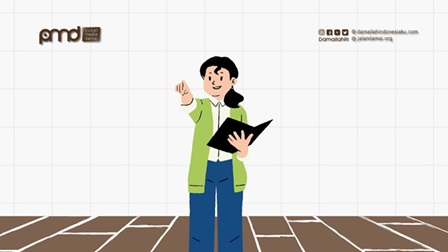Kita sedang menghadapi sebuah paradoks besar dalam dunia pendidikan. Generasi muda kita kini memiliki akses tak terbatas ke informasi. Dalam hitungan detik, Google, YouTube, hingga ChatGPT siap menyajikan data apa pun yang mereka minta.
Ironisnya, di tengah banjir informasi ini, mereka justru tenggelam dalam krisis makna. Siswa kita mungkin pintar secara akademis, menguasai banyak “fakta”, tetapi banyak dari mereka yang bingung akan identitas, gamang soal tujuan hidup, dan rapuh secara nilai.
Inilah ruang kosong yang sangat berbahaya. Kekosongan makna adalah lahan subur yang paling disukai oleh kelompok radikal teroris.
Saat pendidikan formal gagal memberikan “mengapa” dan “untuk apa” kita hidup, kelompok ekstremis akan hadir dengan cepat. Mereka menawarkan jawaban yang paling simpel, paling hitam-putih, dan paling destruktif. Mereka menawarkan identitas instan, rasa memiliki, dan sebuah makna perjuangan yang sesat bagi jiwa-jiwa muda yang sedang mencari pegangan.
Sebelum isu pendidikan yang buruk ini ditunggangi sepenuhnya, kita harus berani mengubah mindset pendidikan kita. Ini bukan lagi soal siapa yang paling cepat menghafal, tapi siapa yang paling kuat memaknai hidupnya.
Selama ini, sistem pembelajaran kita seperti terjebak pada apa yang disebut transmisi ilmu. Dalam model ini, guru berfungsi sebagai penyampai materi an sich, dan siswa adalah penerima pasif. Fokus utamanya adalah penguasaan konten, hafalan rumus, dan pencapaian nilai atau skor tes setinggi-tingginya.
Masalahnya? Di era digital, peran ini sudah usang. Jika guru hanya sebatas mentransfer ilmu, mereka sedang berkompetisi dengan Google dan AI—dan saya yakin mereka pasti kalah.
Hasil dari model ini adalah apa yang kita lihat sekarang: generasi yang pintar tetapi tidak bijak. Mereka menguasai fakta, tetapi tidak memahami relevansi fakta itu dengan kehidupan nyata. Pembelajaran cepat dilupakan karena tidak ada koneksi emosional dan spiritual.
Model transmisi ilmu ini telah gagal membangun satu hal yang paling krusial di zaman ini, yaitu resiliensi. Ketahanan terhadap hoaks, ketahanan terhadap polarisasi, dan yang paling genting, ketahanan terhadap bujuk rayu radikalisasi.
Solusinya adalah transformasi fundamental, yakni pergeseran dari transmisi ilmu menjadi transmisi makna.
Transmisi makna tidak berarti menghapus pelajaran akademis. Sebaliknya, ia mengintegrasikan nilai, konteks, dan relevansi hidup ke dalam setiap mata pelajaran. Sejarah misalnya bukan lagi hanya hafalan tanggal dan nama, tetapi menjadi ruang refleksi untuk mengambil keputusan yang lebih bijak hari ini.
Proses ini terjadi ketika guru menerapkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). Sebagai contoh, guru tidak hanya mengajar apa itu puasa secara teknis menahan makan dan minum, tetapi membimbing siswa untuk merenungkan makna spiritual di baliknya, dampak sosialnya, dan relevansinya untuk melatih empati serta disiplin diri.
Ini juga terjadi melalui dorongan rasa ingin tahu, di mana guru tidak lagi menjadi satu-satunya pemberi jawaban, melainkan seorang fasilitator yang memancing pertanyaan kritis. Siswa yang kritis dan terbiasa berdialog secara sehat tidak akan mudah terpengaruh oleh propaganda satu arah yang kaku. Yang terpenting, transmisi makna ini harus berakar kuat pada budaya kita sendiri, pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Inilah fondasi karakter yang menjadi benteng terkuat kita.
Di sinilah letak peran guru yang tak tergantikan. Untuk bisa mentransmisikan makna, guru tidak bisa lagi hanya menjadi pengajar. Mereka harus berevolusi menjadi murabbi—seorang pembimbing kehidupan, pendidik karakter, dan teladan yang autentik (uswatun hasanah).
Penelitian telah membuktikan hal ini. Sebuah studi menunjukkan bahwa sikap dan keteladanan guru memiliki pengaruh langsung yang sangat kuat, mencapai 73%, dalam mencegah radikalisasi dan membangun karakter siswa.
Radikalisasi sering menyasar anak muda yang merasa terasing, tidak dihargai, dan tidak memiliki teladan. Kita tidak punya banyak waktu. Bom waktu ini terus berdetak di ruang-ruang kelas kita. Mengubah mindset pendidikan adalah panggilan mendesak bagi para pendidik.
Ini juga adalah desakan bagi pembuat kebijakan untuk memberi ruang bagi fleksibilitas dan pendidikan karakter yang nyata, bukan sekadar administrasi.
Google bisa memberi anak kita ilmu. Tapi hanya guru yang berkarakter dan peduli yang bisa memberikan mereka makna, integritas, dan keteladanan untuk menjalani hidup. Kita harus menyelamatkan pendidikan kita untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini dari ancaman kehancuran makna.