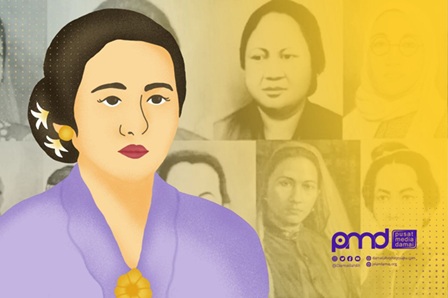Saya tak pernah tahu apakah Kartini pernah mengenal Nyi Ageng Serang, salah seorang perempuan penasehat perang Pangeran Dipanegara, atau Nyai Harjo Besari, seorang washitah atau mursyid perempuan pertama di Indonesia. Sebab, tuntutannya akan “kebebasan perempuan” dalam berbagai keluh-kesahnya sama sekali tak mencerminkan nasib para perempuan di Nusantara sejauh ini.
Namun, tafsir selama ini atas berbagai keluh-kesah Kartini seolah menempatkan kebudayaan Nusantara telah mempersempit, dan bahkan menutup sama sekali, ruang bagi para perempuan untuk mereguk sejuknya air kebebasan, untuk tak mengatakannya mendapatkan fungsi kebudayaan sebagaimana para lelaki.
Bagi saya, Kartini adalah seorang modernis yang memang senantiasa terjebak pada standar atau parameter kebudayaan “Barat” dalam menyikapi kebudayaan “Timur.” Dan celakanya, seolah para perempuan Indonesia pasca kemerdekaan tercekoki oleh berbagai keluh-kesahnya dalam menghadapi dan menyikapi berbagai problem kebudayaan Indonesia, utamanya problem gender.
Seandainya saja, sebagai misal, Nyai Harjo Besari dapat menjadi seorang mursyid tarekat perempuan, kita dapat membayangkan apalagi sekedar peran dan fungsi sebagai pejabat publik atau bahkan agamawati—mengingat ia juga pernah mengkritisi keadaan penyebaran agama Islam di masanya pada seorang teman korespondensinya di Eropah.
Dunia spiritualitas tentu saja adalah sebuah dunia yang jauh lebih rumit dari sekedar dunia politik, sosial, dsb. Sebab, secara gamblang, ia dianggap sebagai satu-satunya dunia yang dianggap langsung berkaitan dengan turut-campur Tuhan, tak sebagaimana dunia sosial ataupun politik yang lebih berdasarkan turut-campur uang, citra, dan pengaruh.
Kita dapat membayangkan bagaimana beratnya seorang Nyai Harjo Besari ketika paham terhadap apa yang kini dikenal sebagai watak patriarkal agama Islam, semisal konsepsi Tuhan yang mayoritas cenderung dianggap maskulin, apalagi dalam berbagai dzikir tarekat yang lebih menggunakan kata ganti ketiga tunggal untuk Tuhan: “Huwa” ataupun “Hu.”
Tetapi, “fakta spiritual” ternyata tak memahami konstruksi spiritualitas semacam itu sebagaimana para feminis kini yang menganggapnya sekedar sebagai bukti watak patriarkal agama Islam. Nyai Harjo Besari, pemegang rantai sanad ke-32 tarekat Syattariyah, yang merupakan keturunan Kyai Ageng Mohammad Besari di Ponorogo, tetap berhak menjadi seorang washitah atau mursyid yang lazim diperankan oleh para lelaki.
Dengan demikian, menjadi sebuah pertanyaan besar benarkah kebudayaan Nusantara yang kita warisi kini menempatkan perempuan jauh lebih rendah daripada lelaki, sebagaimana keluh-kesah sang modernis Kartini yang selama ini diterima begitu saja?
Bagi saya, jelas Kartini atau kebanyakan dari kita cenderung memahami secara harfiah sebuah kebudayaan yang selama ini kita warisi. Taruhlah watak patriarkal yang selama ini dianggap lekat dengan agama Islam. Dalam tarekat Syattariyah di Nusantara, ternyata, seumpamanya dzikir isim gaib “Hu,” tak pernah dipahami sebagai kata ganti ketiga tunggal untuk Tuhan yang maskulin. Namun, “Hu” itu lebih diterima sebagai representasi “Hurip” atau hidup.
Tentang kemulian seorang perempuan secara spiritual, saya pun pernah mendapatkan sebuah teks yang merupakan warisan dari Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo, yang didirikan oleh Kyai Ageng Mohammad Besari, kakek dari mursyid perempuan pertama di Indonesia, Nyai Harjo Besari. Dalam teks itu terdapat kedudukan Fatimah putri sang nabi dan niat mandi bagi para perempuan yang diletakkan sebagai sang wadah dari “Rahsa kang mulya” dan “Rahsa kang sampurna,” yang semuanya itu untuk melengkapi apa yang dikenal sebagai syahadat diri atau “Syahadat Panetep Panatagama.”