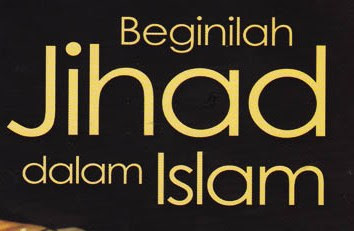Tak pernah menyusut, para teroris dan ekstrimis terus membranding dan menjustifikasi setiap tindakan kekerasan yang dilakukannya dengan kata jihad. Kata ini semakin dilucuti dari maknanya yang lebih subtantif, bahkan diyakini bermakna tunggal: membunuh siapa saja yang diyakini kafir. Karena itulah, penting kiranya menjernihkan maknanya sehingga kita dapat menangkap makna terdalamnya.
Sebenarnya, dalam bentuk apapun, sebuah kekerasan sama sekali tidak dibenarkan oleh agama. Semua agama (khususnya Abrahamic Religions) menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi untuk memecahkan suatu masalah demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bahkan, jalan kekerasan sangatlah kontra-produktif dan akan melahirkan kekerasan-kekerasan baru yang lebih dahsyat (counterinsurgency).
Ironisnya, mereka seringkali mengatasnamakan agama (Jihad fiy sabilillah; holy war; crussade) untuk mengabsahkan adanya kekerasan. Hans Wehr dalam A Dictionary of Modern Written Arabic (1976) menulis, Jihad : fight, battel, holy war (against the infidles as a religious duty). Ar-Raghib al-Asfahani dalam al-Mufradat li Gharib Al-Qur’an menyatakan bahwa makna Jihad adalah mencurahkan kemampuan dalam menahan serangan musuh.
Jihad berasal dari akar kata jahada-yujahidu-jihadan yang mempunyai arti “sukar” atau “sulit” dan “sungguh-sungguh”. Menurut Ibn Faris (w. 395 H) mengatakan bahwa setiap kata yang terbentuk dari huruf j-h-d pada mulanya bermakna “kesulitan” atau “kesukaran” dan yang sepadan denganya. Adapula yang mengartikan jihad berasal dari kata juhd yang berarti kemampuan. Dinamai demikian karena jihad memerlukan pengerahan segala kemampuan yang dimiliki dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Quraish Shihab, 2000: 501)
Dalam al-Qur’an ternyata jihad tidak selamanya bermakna konfrontasi fisik dengan musuh. Ayat jihad dalam al-Quran seluruhnya Madaniyah, atau diwahyukan pasca Nabi Hijrah ke Madinah (622 M), kecuali 25: 52 yang disepakati ulama sebagai ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah.
Ayat-ayat jihad pada awalnya mengisyaratkan makna pengorbanan dan perjuangan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Tapi uraian fiqh tentang jihad sebagian besar merupakan hasil usaha sistematisasi solusi pragmatis yang diambil Nabi. Titik lemah uraian itu adalah kegagalan menangkap regulasi moral yang non-contingen, seolah-olah variabel yang paling krusial dibalik jihad adalah mandat Ilahi untuk melancarkan peperangan. (Samsurrizal, Islamika No 4 hlm 93).
Dus, konsep “Jihad” yang diteladankan oleh Muhammad bukan untuk memusnahkan (al-qital) kelompok tertentu, tetapi perlawanan terhadap ketidakadilan, deviasi, dan patologi sosial. Karena itulah, istilah jihad tidak serta merta menunjukkan arti kekerasan fisik (al-qital bi al-shaif). Akan tetapi, jihad merupakan media atau sarana untuk menumbangkan otoritarianisme, arogansi, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
Hal ini sangat jelas dalam hadist nabi ketika usai berperang yang sangat dahsyat, bahwa kita kembali dari peperangan yang kecil (perang secara fisik) menuju perang besar, yakni melawan hawa nafsu. Bahkan, Tuhan pernah mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa satu orang, maka ia seolah-olah menyelamatkan nyawa semua orang (QS.5; 32) dan membela yang teraniaya (QS. 22; 39-40). Tidakkah kasih sayang, kejujuran, kesopanan (al-akhlaq al-karimah) dan kesucian karakternya –bukan dengan kekerasan–merupakan kunci keberhasilan Muhammad menyebarkan Islam ?
Jika demikian, membenarkan kekerasan atas nama agama sama sekali tidak bisa dibenarkan. Juga, pemahaman mereka tentang agama tidak komprehensip dan kaku (rigid). Padahal, semua ayat Al-Qur’an memiliki langgam tertentu sesuai dengan konteksnya, sehingga memahaminya juga diperlukan adanya pemahaman tentang konstek sosial-budaya yang mengitarinya. Ia hadir bukan di padang pasing yang kering, hampa akan peradaban manusia, tetapi dihadapan aneka spektrum historis-sosiologis di suatu kawasan tertentu, Mekkah dan Madinah.
Karena itulah tindakan teror tidak muncul dari semangat agama (Islam). Sebab, Islam yang seringkali distigmakan oleh Barat sebagai “agama pedang”, ternyata justru mengajarkan humanisasi, anti-kekerasan (QS. 4; 19, 42; 40), kesabaran (QS. 16; 126) taqwa (QS. 16; 128) serta sejumlah nilai-nilai kemanusiaan lainnya.
Oleh karena itu, mengubah performance agama yang sangar, rigid dan menakutkan itu menjadi agama yang progresif-humanis adalah niscaya. Sebab agama idealnya lahir to humanize human being, memanusiakan manusia. Agama dengan visi dan misi profetisnya harus benar-benar diupayakan dan direalisasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab jika nilai-nilai luhur dari agama mengendap menjadikan manusia tentram dan damai dalam interaksi sosial. Jika tidak, agama akan kehilangan “makna” di tengah-tengah realitas sosial.