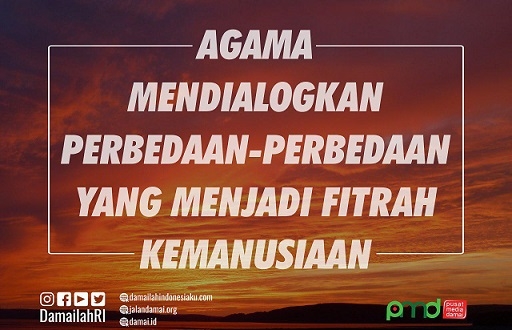Secara fitrah, agama apapun yang ada di muka bumi ini niscaya mengajarkan kebaikan dan cinta kasih pada seluruh alam. Jika nyatanya pemeluk agama justru mengajarkan berbagai kekerasan atau kebencian, dengan aneka kepentingan pragmatis di baliknya, maka sejatinya ia telah keluar dari ruh dan jiwa utama agama. Peran agama untuk menyatukan sesama menjadi hilang.
Dalam konteks inilah, ketika berada dalam genggaman orang-orang yang salah dan memiliki kepentingan pragmatis, agama yang semestinya mengusung nilai positif mendadak menjadi alat yang membahayakan bagi kemanusiaan. Telah banyak peristiwa yang menjadi bukti sahihnya, bisa berupa tindak kekerasan, persekusi maupun bahkan perang “suci” (sesungguhnya tidak ada perang yang suci).
Melihat fakta kekerasan, perang, pertikaian, saling bunuh, dan aneka teror merajalela, yang acapkali dilatari sentimen agama, tepat kiranya jika Charles Kimball, Guru Besar Studi Agama Universitas Wake Forest, AS, dalam bukunya, When Religion Becomes Evil (2002), menengarai agama acapkali justru menjadi bencana kemanusiaan bukan perekat perdamaian. Saat itulah agama menjadi busuk dan rusak, katanya.
Menurut Kimball, pangkal kebusukan dan kerusakan agama itu ada lima. Pertama, kala pemeluk agama mengklaim kebenaran (truth claim) agamanya sebagai satu-satunya dan yang mutlak. Yang lain dinilai salah kaprah dan karenanya patut dienyahkan dari muka bumi. Memang benar, penganut agama sudah semestinya meyakini agama atau keyakinannya sebagai yang terbaik. Namun tidak semestinya serta-merta menutup potensi kebenaran yang ada pada pihak lain.
Kedua, munculnya fanatisme buta para pemeluk agama, pada pemimpin keagamaan mereka. Ingat ucapan Karl Marx: agama itu laksana kekuasaan. Siapa menggenggam agama, dialah penguasa yang dapat melakukan apa saja. Fanatisme ini akan menghadirkan sikap merasa benar sendiri dengan potensi menyalahkan pihak lain yang berbeda. Fanatisme juga akan melahirkan gaya keberagamaan bak kaca mata kuda. Hitam putih dan tegak lurus. Ujungnya, persekusi atau kekerasan pada pihak lain akan dilakukan untuk memenangkan fanatismenya.
Ketiga, pemeluk agama mulai gandrung merindukan zaman ideal atau the golden age. Tak cukup hanya merindukan, mereka pun bertekad mengusung zaman itu ke masa kini, termasuk dengan segala cara. Padahal diketahui, setiap zaman senantiasa ada konteks dan sejarahnya sendiri-sendiri. Tidak semestinya sejarah masa lalu yang berbeda ruang lingkupnya, dipaksaterapkan untuk konteks hari ini yang sudah demikian berbeda dalam segala sisinya. Ini juga berpotensi melabrak tatanan modern hanya karena untuk memenangkan imajinasi masa lampaunya.
Keempat, kala pemeluk agama menyetujui dan mentolerir terjadinya “tujuan membenarkan segala cara.” Mencapai tujuan mulia itu sudah seharusnya dilakukan sekuat tenaga. Namun dengan catatan, cara yang ditempuh tidak melabrak norma-norma kemanusiaan universal. Tujuan yang baik, jika dilakukan dengan cara yang buruk, maka akan menjadi buruk. Amar ma’ruf yang dilakukan dengan kemungkaran, otomatis justru menjadi kemungkaran itu sendiri. Karena itu, tegakkanlah nilai-nilai agama dengan keluhuran dan kemuliaan, bukan dengan membenarkan segala cara!
Dan kelima, bila crusade (perang suci) diteriakkan. Sejatinya tidak ada perang yang suci. Perang selalu kotor dan penuh intrik, dendam, kebencian dan amarah. Perang suci hanyalah bungkus yang digunakan untuk menyamarkan kekotoran itu. Dan, klaim perang suci itu faktanya hanya menyebabkan ribuan bahkan jutaan nyawa meregang. Darah bertumpahan di mana-mana. Tak jarang mereka yang tak berdosa turut menjadi korban. Perang Salib menjadi salah satu contoh “terbaik”nya. Dalam konteks modern, teriakan atau pekikan perang suci semestinya dihindari, guna mewujudkan fitrah damai agama.
Dalam bahasa Rudolf Otto, barangkali kelima hal inilah yang disebut mysterium tremendum (misteri yang menggentarkan), dalam kaitan hubungan antara manusia dengan Tuhan (agama). Banyak hal-hal yang di luar nalar, jika manusia memiliki fanatisme buta pada ajaran agamanya. Bahkan, apa saja bisa dilakukan, hatta tindakan yang di luar nalar sekalipun. Inilah misteri agama dan pemeluknya.
Dalam konteks Islam, agama sesungguhnya hadir untuk menemukan titik persamaan dengan mereka yang dinilai berbeda, bukan justru memperuncing perbedaan. Inilah yang sering disebut sebagai kalimah sawa (titik persamaan). Di mana titik persamaan terpuncak itu? Tak lain kecuali titik kemanusiaan; bahwa semua yang ada di alam raya ini tak lain adalah makhluk Allah yang semestinya saling merindui, menghormati dan memuliakan satu dengan yang lainnya. Keindahan akan tampak dari kesamaan ini.
Tak elok kiranya, sesama hamba Allah saling berhadapan dengan garang hanya karena perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Perbedaan hanyalah sarana yang sengaja Allah ciptakan sebagai alat untuk saling mengenal (li taarafu). Karena itu, Islam mengajarkan konsep kebersaaman berupa musyawarah (berembug) untuk menyelesaikan dan mensinergikan berbagai perbedaan.
Dengan demikian, fungsi agama sesungguhnya untuk mendialogkan perbedaan-perbedaan yang menjadi fitrah kemanusiaan. Di situlah agama akan menemukan relevansinya dalam kehidupan sejati. Dan, saat itulah agama benar-benar menjadi kebutuhan manusia modern yang tidak bisa dinafikan.