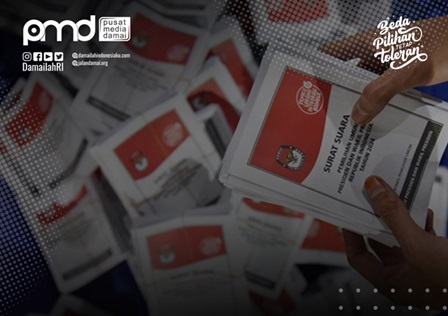Pemilu selalu dianggap sebagai variabel tunggal yang menentukan masa depan demokrasi. Itulah mengapa semua kekuatan politik dan gerakan sosial berjibaku di arena tersebut. Padahal, pemilu juga sarat dengan perpecahan, keterbelahan, dan ego-ego politik yang selalu menjadi “kesempatan” bagi para kelompok fundamentalis untuk mendelegitimasi demokrasi itu sendiri melalui formalisasi “syariat” Islam.
Obsesi ini sebetulnya sudah muncul sejak sesaat setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaanya. Hal ini bisa dilihat dari proses perumusan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai pada masa Orde Lama. Meski pada era Orde Baru isu ini tidak begitu menjadi sorotan media, namun sesaat setelah kejatuhannya (era Reformasi) isu ini kembali muncul ke publik.
Pasca Orde Baru, utamanya setelah memasuki Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka, wacana “islamisasi” selalu keluar di momen-momen pemilu. Satu praktik demokrasi ini selalu menjadi momentum untuk membenturkan “kesucian” hukum-hukum Tuhan dengan “kafirnya” sistem buatan manusia.
Salah satu ayat yang selalu dijadikan dalil untuk melegalkan ide “islamisasi” ini adalah QS. Al Maidah: 49,
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”
Menurut kaum fundamentalis ayat tersebut adalah perintah atas diwajibkannya penerapkan hukum Islam secara total di muka bumi. Siapa pun masyarakatnya dan apa pun agamanya harus tunduk pada penerapan hukum Islam dalam suatu negara. Beberapa akun fundamentalis misalnya menghardik pemilu sebagai syirik akbar dan jari-jari bekas cap tinta pencoblosan itu, katanya, akan menjadi saksi di neraka karena telah menyekutukan Allah.
Tetapi, ide “islamisasi” ini perlu ditinjau ulang. Makmun Rasyid dalam buku HTI Gagal Paham Khilafah membagi rumusan maksud islamisasi dalam dua hal; yaitu pertama, Islam yang hanya secara legal-formal dalam bentuk fisik, dan kedua, Islam sejati yang benar-benar menanamkan nilai Islam. Jika dibredel, obsesi kaum fundamentalis itu tampaknya hanya memposisikan Islam sebagai ideologi politik (legal formal), bukan Islam sebagai laku hidup (substansial). Padahal, formalitas itu tidak lebih penting dari perilaku dan moralitas manusia yang hidup dalam suatu komunitas.
Oleh karena bahan bakar propaganda formalisasi “syariat” dan “khilafah” ini adalah disintegrasi masyarakat, maka kesadaran persatuan dan persaudaraan sudah cukup menjadi imun untuk mencegah paham-paham ini. Lubang besar kontestasi politik sebetulnya bisa ditambal dengan semangat kebersamaan agar tidak menjadi ladang subur propaganda radikal terorisme pasca pemilu. Namun kita juga sadar, realisasinya tak semudah jentikan jari Thanos.
Ilustrasinya begini, di Amerika Serikat, polarisasi dan keterbelahan politik bukan sesuatu yang baru dan berbahaya. Polarisasi turut membuat demokrasi di AS menjadi salah satu yang paling tua dan dewasa. Melalui proses inilah lahir berbagai perubahan progresif yang menuntun perubahan pula di negara lain di dunia, seperti pemenuhan HAM bagi minoritas hingga pemberdayaan perempuan.
Namun ketika rezim Joe Biden dimulai, polarisasi politik di masyarakat AS justru kian ekstrem. Tidak hanya bersifat politis, polarisasi politik ini bahkan telah menembus hingga ke tingkat personal. Artinya, hal yang dipersoalkan antara para simpatisan Partai Republik (liberal-progresif) dan Demokrat (eksklusif-konservatif) tak lagi soal substansi kebijakan politik, tetapi telah melebar ke soal asumsi stereotip. Situasi ini membuat jurang di tengah masyarakat semakin lebar dan mengakar hingga bertransformasi menjadi persoalan identitas.
Fenomena ini terekam oleh hasil studi dari PEW Research pada September 2019. Ketika ditanya, sebagian besar simpatisan Partai Republik merasa bahwa para pendukung Partai Demokrat merupakan orang-orang yang berpikiran tertutup (64%), tidak patriotik (63%), dan tidak bermoral (55%). Sementara sebagian besar dari pendukung Partai Demokrat juga merasa bahwa simpatisan Partai Republik berpikiran tertutup (75%), tidak bermoral (47%), dan bodoh (38%). Di negara dengan sistem demokrasi tertua saja keterbelahan ini bisa berpotensi mengarah pada perpecahan, apalagi di Indonesia yang baru seumur jagung.
Di Indonesia, polarisasi tidak hanya berdampak pada perpecahan di akar rumput namun juga ancaman terhadap fondasi dan falsafah bangsa Indonesia, yakni demokrasi, UUD 45, dan Pancasila. Tentu kita tak menginginkan Negeri Nyiur Melambai ini berubah menjadi negeri mencekam di bawah rezim seperti ISIS dan Taliban.
Jika para kaum fundamentalis menyebaran propaganda dengan pendekatan teks-teks suci, maka kita mempunyai kewajiban moral untuk meluruskan pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang, dengan semangat humanisme-nya menekankan persatuan, kesetaraan, dan persaudaraan dari seluruh individu. Sari pati ajaran Islam terletak pada pengesaan Tuhan, persaudaraan umat manusia, keadilan sosial, dan konsep umat menunjukkan pesan universalnya perihal persatuan dan inklusivitas.
Di era media baru, media sosial memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik. Oleh sebab itu, diseminasi pesan-pesan persatuan perdamaian perlu diduplikasi sebanyak mungkin untuk menutup celah-celah rentang konflik yang bisa dieksploitasi oleh kelompok radikal terorisme. Kita tentu tak boleh naif bahwa kesuksesan pemilu bukan semata dilihat dari lahirnya para pemimpin baru, namun juga bagaimana memitigasi ancaman-ancaman tak kasat mata yang memanfaatkan momentum pemilu.