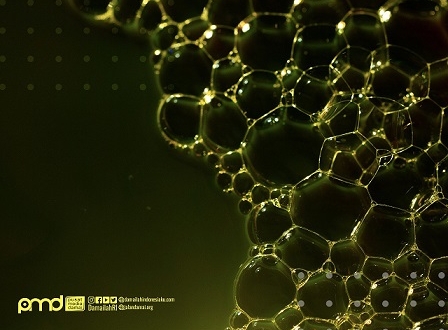Pemberontakan pada dasarnya adalah salah satu faktisitas manusia, yang merupakan cara beradanya. Demikianlah tali simpul yang dapat ditarik dari seorang Albert Camus. Sastrawan Perancis peraih nobel sastra ini, yang seusai itu meninggal karena mobilnya menabrak sebuah pohon, memilah pemberontakan manusia menjadi pemberontakan metafisik dan pemberontakan historis.
Sebagaimana laiknya para eksistensialis, Camus menitikberatkan pula pada aksi daripada refleksi. Tilikannya pada tema pemberontakan tak dapat dilepaskan dari asumsi besar eksistensialisme bahwa yang terpenting bukanlah apa hidup itu, namun bagaimana orang itu hidup. “Existence precedes essence,” catat Sartre yang merupakan kawan Camus dalam pemopuleran filsafat di café-café dan lalu menjadikannya semacam gaya hidup.
Pengutamaan aksi dari pada refleksi dalam eksistensialisme ini merupakan derivasi dari fenomenologi Husserl yang menyingkapkan bahwa ternyata dunia penghayatan atau apa yang dialami manusia terlebih dulu terbentuk daripada dunia refleksi atau dunia pemikiran mereka. Maka tak salah ketika Camus, dalam The Rebel, menyimpulkan bahwa “Aku memberontak, karena itu aku ada.”
Kisah manusia pada dasarnya, menurut sastrawan yang konon sempat menjeda kisah kasih antara Sartre dan Simone de Bouvoir ini, adalah sebuah kisah pemberontakan. Ia merunut dari kisah-kisah pemberontakan Kain atau Qabil yang membunuh Habel atau Habil sebagai pemberontakan metafisik yang kemudian bersambung pada Ivan Karamazov, seorang tokoh novel Dostoyevski, yang popular dengan kesimpulannya: “Nothing is true, all is permitted.”
Entah kenapa, dari renungan Camus itu, pemberontakan-pemberontakan metafisik itu seakan-akan melatari pula kisah-kisah pemberontakan dan revolusi dalam sejarah manusia. Komunisme Soviet, seumpamanya, juga tercatat menghalalkan segala cara agar masyarakat—dari tahap masyarakat feodal—dapat berlanjut ke bentuk masyarakat komunis. Maka di sinilah prinsip Lenin yang terkenal itu mendapatkan konteksnya, bahwa kekerasan adalah bidan bagi perubahan.
Dari tilikan eksistensial itu orang pun akan mafhum bahwa, pertama, terorisme ternyata sudah ada dan berlangsung sejak lama. Kedua, bahwa latar-belakang terorisme itu tak semata bernuansa keagamaan. Dan ketiga, apa yang dikenal sebagai terorisme itu, entah dengan alasan apapun, terpaksa menyalahi segala tertib kehidupan: aturan-aturan baik yang metafisik (yang bernuansa keagamaan dan tabu-tabu dalam masyarakat tribal) maupun yang fisik (kesepakatan, hukum-hukum, dan perundang-undangan).
Dari tilikan eksistensial itu dapat dikatakan bahwa pemberontakan memang adalah salah satu cara dimana otentisitas, satu ide agung dalam eksistensialisme, menyeruak yang kemudian menyebabkan orang menjadi seseorang. Namun demikian, otentisitas ternyata hanyalah seonggok tipu daya modernitas, sebagaimana yang diungkapkan oleh para postmodernis yang banyak mempertanyakan premis-premis pemikiran modern dimana eksistensialisme mendasarkan diri.
Alasan-alasan pinggiran, simpul logika postmodern, selalu saja yang menjadi dasar dari ide-ide ataupun aksi-aksi yang tampak agung. Taruhlah Habel yang membunuh Kain yang bisa saja hanya karena tampang Kain yang buruk. Atau Sokrates yang pernah diagung-agungkan oleh Plato sebagai guru kembara sejati atau pahlawan tanpa tanda jasa yang bisa jadi hanya karena menghindari isterinya yang terkenal jelek lagi judes. Maka, pemikiran-pemikiran maupun aksi-aksi pemberontakan seperti makar bisa jadi hanya karena masalah-masalah sepele sebagaimana yang tersebut.