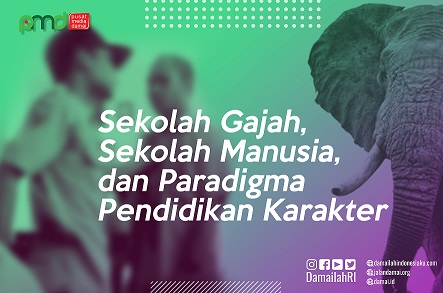Pernahkah mendengarkan cerita “Sekolah Gajah”? Sekolah yang didirikan pada masa orde baru yang didirikan di Way Kambas, Lampung. Cerita ini sangat populer bagi mereka yang menggeluti dunia pendidikan terutama sebagai fasilitator. Cerita ini juga patut kita refleksikan ketika melihat video siswa menantang guru di SMP PGRI Wringinanom Gresik (02/02/2019). Komentar masyarakat mengarah pada buruknya akhlak siswa. Pun ketika guru menghukum siswa hingga dipenjarakan, komentarnya pun sama.
Solusi yang ditawarkan atas tontonan amoral antara siswa-guru, yang sering kita dengar mengarah pada pendidikan moral, pendidikan karakter. Mulai dari mengubah kurikulum, mengintegrasikan mata pelajaran dengan nilai agama, hingga membuat sistem full day school. Solusi yang ditawarkan atas permasalahan siswa tersebut persis ketika melihat gajah-gajah mengamuk, dalam cerita sekolah gajah.
Kenapa gajah ikut disekolahkan? Karena gajah dianggap semena-mena, membuat onar dan stabilitas di masyarakat terganggu. Gajah dianggap mengganggu petani hingga menyebabkan tidak panen. Gajah juga dianggap merugikan masyarakat transmigran. Alhasil, biang semua permasalahan di masyarakat dianggap bersumber dari gajah.
Semua masyarakat merasa terusik dengan peristiwa gajah. Mereka yang profesinya berburu, setuju kalau gajah sebaiknya ditembak. Berbeda dengan mereka yang memiliki profesi berdagang binatang, lebih setuju kalau diekspor. Mereka justru mendapatkan inspirasi komoditi baru non migas yang bisa diekspor.
Lain halnya dengan mereka yang sehari-harinya memikirkan bagaimana mendayagunakan berbagai potensi demi pembangunan, amukan gajah memberikan gagasan cemerlang. Mereka menyusun konsep dalam bentuk proposal. Ide yang ditawarkannya adalah dengan membuat gajah tidak mengamuk, yaitu dengan cara “dididik”. Atas dasar itu, muncullah klausal, di mana, kapan, bagaimana caranya, siapa pelatihnya, siapa pengelolanya, berapa dan dari sumber mana anggaran belanjanya.
Baca juga :Keluarga sebagai Pilar Pendidikan Karakter
Disetujuilah rancangan “Sekolah Gajah” yang dianggap menjadi solusi utama atas amukan Gajah. Sekolah sudah didirikan untuk melatih gajah agar tidak mengamuk yang menyebabkan kerugian masyarakat. Kenyataan yang patut kita ketahui, di sekolah itu Gajah tidak lagi mengamuk. Mereka tidak membuat onar, tidak merusak tanaman masyarakat.
Jinak, seperti yang diinginkan masyarakat dengan adanya sekolah itu. Gajah itu pun melakukan kerja-kerja untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan suka rela mereka mau mengangkut gelondongan kayu dari hutan untuk dibawa ke tempat penampungan. Berkat para pelatih, yang didatangkan dari Thailand, mereka juga menunjukkan keahlian-keahlian yang semula tidak dimilikinya.
Gajah-gajah mulai bisa memainkan sepak bola. Hingga akhirnya dibentuklah kesebelasan gajah, yang mampu mendatangkan para turis dari berbagai macam negara untuk menyaksikan keajaiban gajah. Mereka tidak menyandang lagi gajah liar, gajah berandalan dan gajah si penjarah. Mereka sudah menunjukkan sebagai gajah yang santun dan mampu mengerjakan yang diinginkan oleh manusia. Gajah-gajah itu juga tidak perlu kembali ke habitatnya, mereka sudah mendapatkan asrama baru.
Saya pernah membagikan cerita tersebut, cerita yang diambil dari buku “Pendidikan Popular”, kepada para calon fasilitator kelas pemikiran Gus Dur di Jakarta tahun 2018. Tanggapan dari para peserta sangat beragam dengan adanya sekolah gajah. Pendapat pertama kali yang muncul, mengamini bahwa langkah menjinakkan sekolah gajah dengan didirikannya sekolah adalah kewajaran dan solusi utama.
Saya memaklumi atas jawaban tersebut. Mungkin itu juga menjadi jawaban saya dulu ketika belum tahu arah cerita tersebut. Kita suka dengan jawaban yang instan menurut kita benar, tanpa mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh gajah. Mengapa gajah itu mengamuk? Tidak menjadi pertanyaan penting bagi kita untuk merumuskan bagaimana tindakan kita menangani amukan gajah.
Solusi semacam itu memang lazim digunakan, pun di dunia pendidikan kita. Banyaknya anggapan bahwa perilaku siswa saat ini jauh dari moralitas masyarakat, misalnya tawuran antar pelajar, siswa yang banyak ketahuan bolos, tidak sopan terhadap guru dan lain sebagainya. Atas dasar permasalahan itu semua, muncullah istilah pendidikan karakter, pendidikan moralitas, hingga siswa dikurung selama seharian di sekolah agar tidak melakukan hal-hal buruk di luar sekolah.
Solusi yang ditawarkan terhadap amukan gajah dan amukan siswa kepada guru dan kepada siswa lainnya, mengarah pada satu tujuan yaitu upaya penaklukan. Sekolah gajah diupayakan agar gajah tidak lagi merusak perkebunan, tidak merusak tanaman dan properti masyarakat. Mereka dijinakkan agar tidak merugikan masyarakat, bahkan mereka dipekerjakan untuk memenuhi hasrat manusia.
Masyarakat tidak menyadari bahwa amukan gajah juga disebabkan olehnya. Menebang hutan untuk memenuhi hasrat pribadinya. Mengusik rumah para gajah, hingga mereka merusak tanaman dan rumah masyarakat.
Penaklukan Moral?
Saya masih ingat betul, bagaimana teman satu kelas dulu yang mempunyai niatan akan melakukan tindakan yang bodoh, menantang gurunya ketika sepulang sekolah. Semboyan guru: digugu lan ditiru (orang yang dipercaya dan diikuti), sudah dilupakan ketika teman saya tadi sedang emosi. Dia emosi bukan tanpa sebab, perlakuan guru dianggap tidak adil baginya.
Beruntung, teman saya hanya sekadar niatan yang diceritakan. Kalaupun jadi melakukan hal demikian, saya yakin bahwa yang disorot oleh masyarakat adalah perlakuan siswa yang sangat buruk terhadap gurunya. Ia tidak bisa menahan emosi yang berlebihan tidak seperti teman-teman yang lain yang rela memendam rasa emosi karena mematuhi guru adalah segala-galanya.
Dari kasus teman saya tersebut, kemudian siswa yang menantang gurunya di Gresik, dan kasus-kasus lainnya ada hal yang sebenarnya patut disoroti. Relasi siswa-guru seperti rakyat kepada rajanya. Guru adalah orang yang dianggap segalanya di sekolah, sebagai orang yang memberi ilmu dan siswa tugasnya adalah mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh guru.
Relasi guru sebagai subjek dan siswa sebagai objek, secara nyata memang masih langgeng di dunia pendidikan formal kita. Kritik terhadap sistem semacam itu memang sudah banyak, namun tidak memberikan dampak signifikan, kecuali membuat sekolah dengan paradigma baru. Sekolah alam, sanggar anak alam dan sekolah-sekolah serupa menjawab kegelisahan itu dengan memperbaiki relasi siswa dan guru. Bahkan istilah “guru” diubah menjadi fasilitator, menandakan mengubah paradigma cara mengajarnya. Sumber pengetahuan tidak hanya dari guru, melainkan juga dari siswa dan alam sekitar.
Memandang tontonan amoral yang dilakukan oleh siswa kepada guru, memang sangat menyesakkan. Lebih menyesakkan lagi kalau kita hanya menyalahkan siswa, tanpa mempertanyakan mengapa mereka melawan guru. Mengapa mereka membolos sekolah, dan mengapa mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki oleh sekolah dan masyarakat secara umum.
Pada perkuliahan psikologi pendidikan lanjut, saya mempertanyakan mengapa fokus perkuliahannya mengarah menangani siswa-siswa yang “bermasalah”. Asumsi saya, ada yang patut disoroti selain siswa, yaitu paradigma guru yang dianggap sebagai sumber pengetahuan pertama. Padahal guru juga bisa belajar kepada siswa, ketika dia tahu siswa juga tahu ia bisa berperan sebagai moderator, dia tahu siswa tidak tahu ia bisa berperan sebagai motivator, dia tahu siswa tidak tahu ia bisa berperan sebagai narasumber, dan ketika guru tidak tahu dan siswa tidak tahu ia bisa menjadi mediator.
Kekerasan siswa kepada guru pun sebaliknya, memang tindakan yang tidak seharusnya terjadi dan sangat disayangkan. Menyalahkan siswa seutuhnya tidak akan memberikan solusi. Kita patut mengevaluasi bersama bagaimana paradigma pendidikan kita memperlakukan siswa dan guru, sehingga terjadi pendidikan yang sesuai dengan dicita-citakan.