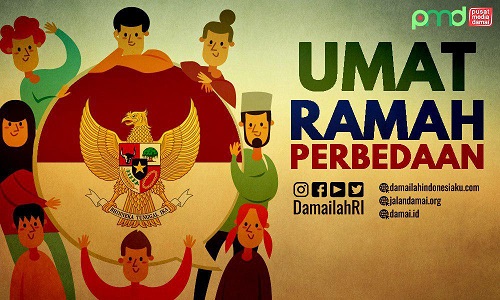Perbedaan kerap dianggap sebagai barang yang asing di masyarakat kita. Buktinya, ada banyak kasus kekerasan yang terjadi lantaran diri merasa paling benar, lalu menyalahkan pandangan lain yang berbeda. Terutama dalam masalah memahami teks agama, seseorang kerap menganggap hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu sebagai kebenaran mutlak, sehingga wajib hukumnya untuk mempertahankannya dengan taruhan nyawa.
Jika kita mau sejenak merenung, menjernihkan pikiran, tentu tak bakal terjadi kekerasan baik verbal maupun fisik, lantaran perbedaan. Mari kita sejenak berpikir, alur atau sanad sebuah teks agama, dalam Islam ada al-Qur’an dan al-Hadits, hingga sampai ke tangan kita. Seperti apakah prosesnya?
Mulanya muncul seorang Nabi yang diutus oleh Tuhan, untuk menyampaikan risalah langit. Bagaimana al-Qur’an diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw., lalu disampaikan kepada umatnya yang sezaman. Umat yang sezaman, bertemu dan bersyahadat mengakui kerasulan Muhammad Saw. dan keesaan Allah Swt., biasa kita sebut sebagai sahabat. Merekalah yang menyokong Nabi Saw. dalam berdakwah, hingga Islam bisa tersiar di berbagai pelosok negeri.
Pada masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup, perbedaan telah ada di dalam tubuh muslimin. Namun, hal tersebut tidaklah sampai pada perpecahan, karena masih ada Juru Damai yang tidak berbicara selain kebenaran. Ialah Rasulullah Saw., dan perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat, seketika bisa diatasi hanya dengan berkonsultasi kepada beliau.
Perbedaan kian meruncing sepeninggalan Nabi Muhammad Saw. Di ujung usianya, beliau berpesan kepada umatnya agar berpegang teguh kepada al-Qur’an dan al-Hadits. Inilah yang menjadi pedoman hidup seorang muslim, sehingga hidupnya tidak tergelincir dalam kesesatan, yang kelak diganjar murka di akhirat.
Terlebih setelah masa sahabat berakhir, masa-masa berikutnya semakin banyak perbedaan. Bahkan dalam sejarah Islam, banyak ulama yang dipaksa mengikuti madzhab resmi negara, yang tentu menciderai semangat “tidak ada paksaan dalam beragama”. Padahal, mazhab itu merupakan produk ijtihad para ulama, yang memiliki kemungkinan benar dan juga salah.
Agar tidak menjadi muslim yang fanatik, ada baiknya kita sadar perbedaan. Bahwa berbeda belum tentu salah. Jalaluddin Rahmat (2007) menjelaskan bahwa setiap madzab memilih satu pendapat dan mempertahankannya dengan berbagai argumentasi. Semua argumentasi itu merujuk kepada al-Qur’an dan al-Hadits. Tetapi, setelah sampai ke kalangan awam, pilihan madzhabnya itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran.
Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa perbedaan pemaknaan atas teks agama, kerap memakan korban orang-orang awam. Mereka menganggap hasil penafsiran ulama-ulama madzhab sebagai kebenaran mutlak. Padahal, yang mutlak benar adalah al-Qur’an, dan penafsiran-penafsiran atasnya merupakan ijtihad dari para ulama yang kompeten dalam bidangnya.
Jika dulu para imam madzhab dalam pertentangan hanya dalam tataran adu argumentasi, mengapa kini sampai ke aksi kekerasan? Ironisnya, bukan hanya orang-orang awam saja yang berselisih, beberapa yang dianggap tokoh agama oleh masyarakat justru malah menebarkan kebencian. Seakan-akan di setiap khutbah atau ceramahnya, ia tengah membangun dinding yang tebal antara golongannya dengan lainnya. Ia seakan-akan sedang berupaya menyatukan umat, tapi caranya dengan menyeragamkan madzhab. Tentu, hal tersebut hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, alih-alih membentuk solidaritas umat.
Umat “Al-Mushawwibun”
Ulama Usul Fikih tempo dulu berbeda pendapat mengenai ijtihad. Ada dua kelompok besar yang berkembang, kaitannya dengan tugas seorang mujtahid, yaitu kelompok al-mukhaththi’un dan al-mushawwibun. Al-mukhaththi’un ialah sebutan bagi penganut paham al-takhthi’ah (kecuali satu, semua salah), yang berpendapat bahwa semua hukum sudah ditentukan Allah, sebelum mujtahid berijtihad. Sehingga, yang berhasil menemukannya pasti benar, dan yang tidak menemukannya sudah tentu salah.
Adapun al-mushawwibun ialah sebutan dari penganut paham al-tashwibah (semua benar), yang berpendapat bahwa untuk kasus yang tidak ada nash-nya, tidak ada hukum tertentu sebelum mujtahid menetapkannya. Karena itu, hukum ialah apa saja yang ditentukan mujtahid berdasarkan perkiraannya. Karena perkiraan, jadi semua ijtihad benar adanya. (Rahmat: 2007)
Dua pandangan yang berbeda tersebut, bisa kita gunakan untuk menilai praktik keberislaman di Indonesia. Masih menurut Jalaluddin Rahmat, bahwa gerakan Islam di Indonesia, tampaknya berangkat dari al-mukhaththi’un ke arah al-mushawwibun.
Sejalan dengan keterbukaan informasi, lanjutnya, perlahan-lahan umat Indonesia mengambil paham al-taswibah. Paham ini telah mendidik jiwa kita agar lebih terbuka, dan melihat perbedaan sebagai suatu yang lumrah dan justru mesti dihargai. Benarkah umat Islam di Indonesia menganut paham al-taswibah dalam merespon perbedaan?
Jika melihat sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita patut bangga kepada perwakilan umat Islam, yang tidak ngotot untuk menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Artinya, founding father kita telah sadar perbedaan, dan dengan rendah hati menerimanya sebagai warna yang indah.
Sebagai generasi penerus, kita tidak hanya dituntut untuk merawat alam Indonesia secara fisiknya saja. Jauh lebih penting dari itu adalah, merawat semangat persatuan yang telah susah payah diupayakan para Bapak Bangsa. Mengupayakan persatuan di negeri yang terdiri dari beraneka agama, suku, ras, dan golongan ini tidak akan berhasil tanpa adanya pemahaman al-taswibah, yang memiliki semangat menghargai perbedaan.