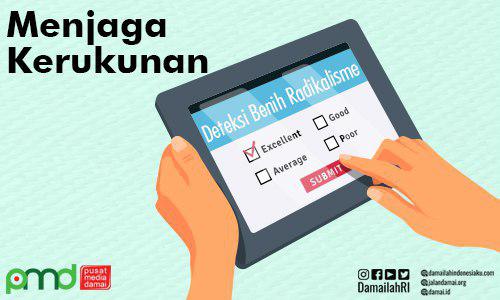Akhir-akhir ini, Indonesia diguncang dengan arus ujaran kebencian yang kian mengkhawatirkan. Saling hujat dan hina di dunia maya telah menjadi makanan sehari-hari, yang tentu menjadi menu tidak sehat untuk otak kita. Aksi-aksi emosional juga kerap melanda Indonesia, baik yang didasarkan pada agama, etnis, golongan, maupun ras. Kesemuanya, merupakan tanda bahaya yang mesti segera direspon pemerintah dan juga masyarakat secara umum.
Generasi milenial, sebagai generasi yang ‘melek internet’, memiliki potensi yang besar dalam kaitannya dengan konflik dan manajemennya. Bagi mereka yang telah menutup diri dari informasi atau kebenaran di luar versi mereka, tentu dengan mudah akan menyalahkan kelompok yang berbeda. Dampaknya jelas, aksi kekerasan yang mereka lumuri dengan legitimasi ayat suci –yang dipahami keliru-, dengan mudah mereka lakukan demi cita-cita yang (dianggapnya) suci.
Generasi milenial yang dianggap bisa berpikir rasional, ternyata memiliki pandangan politik yang eksklusif. Ini yang ditemukan oleh CSIS dalam surveinya selama kurun 23-30 Agustus 2017. Dikatakan bahwa 58,4 persen generasi milenial sama sekali enggan menerima pemimpin yang berbeda agamanya. Sementara yang mau menerima pemimpin yang berebda keyakinan hanya sebanyak 39,15 persen. (Kompas/26/02/208)
Temuan tersebut dapat kita jadikan acuan untuk mendeteksi semenjak dini, kecenderungan generasi milenial, utamanya persoalan pilihan politik. Memang, survei tersebut berbicara dalam ranah pilihan politik. Tapi, itu bisa kita seret ke ranah sosial-kemasyarakatan; bahwa ada kecenderungan alergi atas perbedaan, dan pandangan eksklusif akan membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI.
Lebih lanjut, Wahid Institute dan Lembaga Survei Indonesia merilis 10 kelompok yang sering menjadi sasaran kebencian masyarakat dan kerap menjadi korban kekerasan. Mereka adalah LGBT (26,1 persen), komunis (16,1 persen), Yahudi (10,7 persen), Kristen (2,2 persen), Syiah (1,3 persen), Wahabi (0,5 persen), Buddha (0,4 persen), China (0,4 persen), Katolik (0,4 persen), dan Khonghucu (0,1 persen).
Munawir Aziz dalam Asep Salahudin (Kompas/26/02/2018) menegaskan bahwa dari survei itu tergambar 59,9 persen responden memiliki kelompok yang dibenci. Dari angka ini, sebanyak 92,2 persen tidak setuju jika anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat pemerintah. Sementara 82,4 persen tidak rela anggota kelompok yang dibenci menjadi tetangga mereka.
Di sini memang tidak dikhususnya responden berasal dari kelompok milenial, melainkan masyarakat pada umumnya. Namun, hal ini mengindikasikan betapa mahalnya toleransi di Indonesia. Padahal, negara-bangsa ini didirikan bukan hanya oleh satu kelompok, melainkan bahu-membahu antar kelompok, ras, agama, dan suku. Semuanya memiliki andil dan oleh karenanya memiliki hak dilindungi undang-undang. Hidup di Indonesia bukan lagi membawa identitas kesukuan atau keagamaan, melainkan melebur menjadi satu identitas, yakni warga negara.
Mendeteksi Radikalisme, Merawat Kerukunan
Kenyataan bahwa lini kehidupan masyarakat telah disusupi internet sampai ke lekuk-lekuk terdalamnya, mesti kita waspadai sekaligus kelola. Kenapa mesti diwaspadai sekaligus dikelola?
Satu alasan mengapa mesti diwaspadai adalah, kecenderungan pola pikir eksklusif (yang berpotensi berkembang menjadi paham radikal) generasi milenial setelah berbaur dengan teknologi, efek ‘ledaknya’ akan luar biasa. Bagaimana tidak, orang dengan mengunggah status bernada ujaran kebencian di facebook misalnya, dengan sedikit menyitir ayat suci, bisa dengan mudah memobilisasi massa. Seakan-akan massa merasa senasib-sepenanggungan, lalu beramai-ramai menghujat kelompok yang disasar.
Dampaknya tentu, bagi kelompok yang disasar, akan mendapat –minimal- tekanan psikologis yang cukup menggelisahkan. Terlebih bagi minoritas, yang dengan mudah ditindas hanya kerena perbedaan pilihan keyakinan, bahkan hanya karena warna kulit. Tentu mereka menjadi tidak krasan hidup di negara-bangsa yang (sebenarnya) memiliki falsafah hidup toleran.
Sujiwo Tejo dalam sebuah acara pernah mengatakan bahwa dirinya tidak berani membenci LGBT. Ia mendasarkan sikapnya pada keyakinan bahwa jika membenci LGBT, ia yakin karma akan berlaku. Bahwa jika ia membenci, pasti anak keturunannya kelak ada yang menjadi kelompok yang ia benci. Yang dibenci bukan pelakunya, tetapi perilakunya –dan ini yang sulit.
Prinsip ini sebenarnya bisa ditiru oleh generasi milenial, untuk mengontrol ambisi untuk olok-olok di media maya. Sebaliknya, generasi milenial mesti bisa menjadi nitizen yang cinta damai, dan selalu mengupayakannya dalam setiap aktivitas daringnya.
Jika dulu sebelum internet merangsek masuk ke Indonesia, kita akan familiar dengan aktivitas ronda malam warga setempat. Biasanya, mereka memiliki basecamp berupa gardu yang letaknya tidak jauh dari jalan lalu lalang. Sesekali mereka berkeliling, menjaga keamanan rumah warga, sembari mengambil jimpitan (uang receh) di pagar atau pintu warga –untuk sekadar beli rokok dan kopi.
Begitu pula di era internet. Melakukan ronda di media maya amatlah perlu, untuk menyisir akun-akun yang berpotensi menebarkan kebencian yang bisa merusak kedamaian nitizen. Sementara gardu sebagai basecamp bisa diaplikasikan dengan cara membuat grup, untuk membicarakan perkembangan ataupun temuan-temuan di lapangan dunia maya. Melalui grup ini pula, dibicarakan strategi taktis agar keamanan dan kedamaian nitizen tetap terjaga.