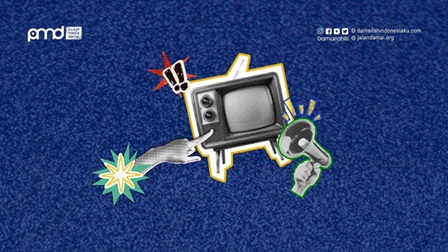Trans7 tengah dihujat netizen di media sosial. Salah satu tayangan mereka dianggap menghina pesantren dan kiai. Sejumlah tokoh NU meradang. Mereka melayangkan protes keras ke Trans7 dan menyerukan boikot stasiun televisi tersebut. Trans7 pun meminta maaf melalui surat yang diunggah di media sosial. Namun, badai kemarahan tampaknya belum akan surut dalam waktu dekat.
Menarik mencermati kasus ini dari sisi industri media massa itu sendiri. Seperti kita tahu, industri media massa konvensional mulai dari surat kabar, radio, sampai televisi, memang tengah ada di ujung tanduk. Badai kebangkrutan industri surat kabar cetak sudah terjadi selama satu dekade belakangan.
Banyak koran dan majalah berhenti cetak atau mengurangi jumlah halaman karena oplah yang terus menyusut. Oplah menurun artinya pendapatan dariiklan pun menyusut. Padahal, iklan lah yang menghidupi media massa. Begitu pula radio dan televisi yang juga mengalami nasib serupa.
Munculnya media sosial mengubah perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Media sosial kini menggeser dominasi media massa konvensional sebagai penyampai informasi. Kue iklan yang tadinya sebagian besar masuk ke media massa konvensional pun kini mengalir ke media sosial.
Kemunculan para mikroseleb seperti TikToker, Youtuber, atau Selebgram juga mengambil alih porsi iklan yang sebelumnya masuk ke media massa konvensional. Pendek kata, industri media massa konvensional tengah menuju senjakalanya.
Mereka dipaksa untuk melakukan apa saja agar bertahan. Ironisnya, alih-alih mempertahankan atau meningkatkan kualitas, banyak media massa yang justru membanting harga dan menurunkan standar kualitas demi mendapat penonton.
Coba lihat bagaimana acara talkshow politik di sejumlah tv, sebagian besar didesain sebagai ajang debat terbuka, penuh amarah, cacian, dan miskin adu gagasan apalagi argumentasi. Debat kusir yang disiarkan live jauh lebih efektif mendongkrak rating ketimbang diskusi ilmiah dengan menghadirkan pakar atau ilmuwan.
Logika media massa kini disetir oleh persepsi bahwa makin receh dan kontroversial sebuah acara, maka kemungkinan viralnya akan tinggi. Media massa konvensional akhirnya terjebak pada gaya dan mekanisme media sosial yang hanya berorientasi pada viral bukan pada kualitas.
Tayangan Trans7 yang dianggap menghina kiai dan pesantren lahir dari logika semacam itu. Tayangan Xpose Uncencored itu sejenis tayangan murah berbiaya rendah. Gambar-gambar yang ditayangkan cukup mengambil dari media sosial, lalu diulang-ulang, lantas dilengkapi dengan narasi voice over yang ditulis dengan gaya berlebihan dan tanpa riset mendalam apalagi wawancara dengan narasumber berita.
Semua dikerjakan ala kadarnya, asal jadi, asal kontroversi, dan asal ramai. Disini logika kapitalisme, modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya menjadi kredo acara tersebut.
Kita tentu patut menyayangkan kasus ini. Media massa apalagi sebesar Trans7 seharusnya mampu memproduksi konten acara yang mencerdaskan dan mencerahkan. Bukan justru ikut arus dengan memproduksi konten kontroversial yang miskin analisis dan abai pada etika jurnalistik. Apa yang terjadi dalam kasus Trans7 ini adalah monetisasi fitnah. Yakni upaya mencari keuntungan finansial dengan menebar fitnah dan kebencian pada kelompok tertentu.
Monetisasi fitnah adalah aib sekaligus dosa besar dalam industri media massa. Peran media massa idealnya adalah sebagai clearing housee alias lembaga yang menjernihkan kekeruhan informasi. Jika di tengah masyarakat beredar informasi yang simpang-siur, maka media massa bertugas menghadirkan informasi yang akurat.
Dalam konteks yang lebih luas, media massa juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kerukunan umat dan masyarakat. Adalah hal yang memalukan jika media massa justru mencari cuan dari kontroversi yang menyulut perpecahan umat.
Ke depan, media massa harus belajar dari kasus ini. Persaingan berebut kue iklan seharusnya tidak lantas mengorbankan umat dan masyarakat. Media massa yang besar dibangun di atas reputasi. Stasiun tv seperti Trans7 misalnya dikenal karena sejumlah acaranya yang edukatif, seperti Laptop Si Unyil, Bocah Petualang, Jejak Si Gundul, Jelajah Nusantara, Jejak Petualangan, dan sebagainya.
Sederet acara itu turut mewarnai tumbuh kembang anak Indonesia. Menghadirkan informasi dengan cara yang unik. Mengangkat budaya Indonesia dengan cara yang jenaka. Jangan sampai, citra positif itu runtuh oleh tayangan nirmutu, khas produk jurnalistik koran merah yang mengumbar kontroversi, seronok, dan abai pada kaidah jurnalistik.