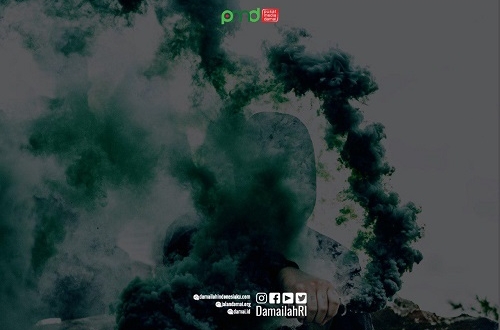Seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba menyeruak kerumunan. Secepat kilat ia menghunjamkan pisaunya ke perut seorang pejabat yang baru turun dari mobil. Sangat sederhana, seolah tak ada yang menyana. Untuk membunuh seorang pejabat tak perlu lagi adanya konspirasi yang rumit seperti yang terekam dalam film Vantage Point (Menakar Gerakan Makar “12:00”, Heru Harjo Hutomo dan Silvia Ajeng Dewanthi, www.harakatuna.com).
Saya pun dapat menyimpulkan modus operandi seperti itu sangat khas jaringan-jaringan teroris kontemporer yang berinduk pada IS (Islamic State). Tiga tahun terakhir ini aksi-aksi teror mereka memang berbeda dengan jaringan-jaringan teroris yang lazimnya berbaiat pada Ayman al-Zawahiri (Al-Qaeda). Seperti jargon kesenian Putu Wijaya di awal kariernya dalam dunia teater, “Bertolak dari yang ada,” para pelaku teror yang berinduk pada IS juga melancarkan aksinya dengan modal seadanya: gunting, pedang, pisau terbang ala ninja Naruto, dst. Di lapangan pun eksekusi mereka tampak pula berlangsung seperti preman jalanan: memakai motor dan meruyak pagar kantor polres kemudian mengayunkan pedang, atau seperti pertarungan Ninja Satoici yang berpapasan dengan musuh dan secepat kilat menghunjamkan gunting.
Jaringan-jaringan teroris yang berinduk pada IS umumnya memang meletakkan simbol-simbol negara sebagai target utama: para pejabat negara dan kepolisian. Secara doktriner, bagi mereka siapa pun yang berupaya menghalangi perjuangan adalah para kafir dzimi. Secara strategis, barangkali, ketika simbol-simbol negara itu sudah dapat dilemahkan—baik simbolik maupun fisik—teror mereka akan lebih mudah untuk dilakukan pada kalangan yang mereka vonis sebagai kafir harbi.
Saya yakin teroris yang melancarkan aksinya pada seorang pejabat negara beberapa waktu lalu—seperti lazimnya para teroris yang berinduk pada IS—adalah para penganut “jalan pintas” ke surga. Latar-belakang kehidupan mereka umumnya kelam: mantan preman, junkies, atau bahkan lonthe. Hal ini memang seperti menjadi trademark organisasi teroris internasional IS. Banyak kekelaman pada kehidupan masa silam mereka. Seorang wartawan Reuters yang menyaru dan masuk dalam sarang mereka mengabarkan kisah-kisah yang berbanding terbalik dengan tampilan mereka di ruang publik: karib dengan alkohol, penjarahan dan seks.
Baca juga:Memutus Mata Rantai Radikalisme
Secara keislaman mereka, saya yakin, tak benar-benar paham dan berwawasan. Pada aras psikologis mereka seperti jiwa-jiwa amatiran: ghirah yang berlebih tapi tanpa dukungan ilmu dan wawasan yang mendalam. Kita tentu pernah bersinggungan dengan jiwa-jiwa amatiran yang tumbuh di sekeliling kita. Jamaknya mereka songong (sok tahu) dan suka menyalahkan orang lain meski hanya baru beberapa hari mendalami agama. Sodorkan al-Qur’an pada mereka, suruhlah baca dan pahami, mereka pasti bungkam. Atau ajak diskusi mereka, seberapa paham mereka tentang khilafah Islamiyah. Atau tanya penguasaan fiqh mereka, bisakah mereka melafalkan niat wudhu dan jinabat-kah mereka seusai sanggama.
Maka terkesan, seperti sinisme para pandir yang membanjir di hari ini, aksi-aksi teror semacam itu hanyalah rekayasa, pengalihan isu, dst. Mereka tak pernah peduli seandainya aksi-aksi yang mereka simpulkan sebagai rekayasa telah memakan korban nyawa. Para pandir itu tak pernah tahu tentang apa, siapa dan bagaimana para teroris kontemporer bekerja. Logika mereka selalu saja logika amatiran yang suka mengambil “jalan pintas.” Karenanya menjadi jihadis adalah satu-satunya pilihan ketika (1) kenikmatan duniawi sudah direguk dan (2) tetek-bengek agama terlalu mengungkung “jiwa bebas” mereka. Doktrin mati syahid—di mana konon mereka tak akan dihisab dan langsung berujung surga—akhirnya menjadi satu-satunya laku utama dibanding laku-laku lainnya. Tak usah belajar fiqh, tak usah melafalkan niat, cukup memiliki—setelah mereguk kenikmatan-kenikmatan duniawi—nyali yang tinggi untuk mati dan memperoleh sepetak surga tanpa hisab.
Logika “jalan pintas” itulah yang menjadi karakteristik jaringan teroris kontemporer—seperti tak ada batas yang tegas antara preman dan lonthe dengan para pejuang keagamaan. Maka, pendekatan terhadap para teroris kontemporer membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan para teroris yang berafiliasi dengan al-Qaeda, JI, ataupun organisasi teroris internasional lainnya.
Saya kira, secara personal, bukanlah pendekatan ekonomi-politik yang tepat untuk membaca geliat mereka. Pada esai saya “Petaka Melankolia” (130518: Merawat Ingatan Merajut Kemanusiaan, idenera.com), orang-orang radikal itu saya betik sebagai para nihilis. Pada dasarnya mereka tak pernah memperjuangkan apapun, tak pernah membela nilai apapun. Sebab pada tataran ideologis mereka buta, tak tahu apa-apa. Pada tataran wawasan keagamaan mereka juga sama saja, tak tahu apa-apa. Mereka para penderita melankolia. Habitus-lah yang menggerakkan mereka, dan bukannya ideologi. Habitatlah yang merekatkan mereka, dan bukannya jaringan. Spontanitaslah yang mencirikan operasi mereka di lapangan, dan bukannya taktik ataupun strategi.