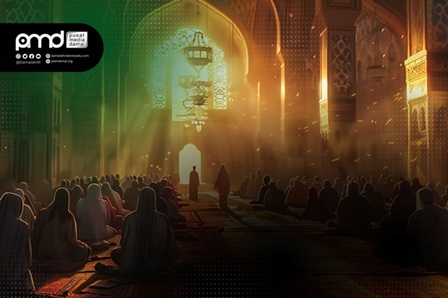Pernah suatu ketika sebuah komunitas seni rupa “kontemporer,” yang dari segi istilah telah menunjukkan semangat “permainan” ala postmodernisme, kerap mengusung tema-tema yang yang tak termaktub dalam narasi agung atau ideologi mainstream: “khilafah,” “hijrah,” “syari’ah,” dsb. Ketika melihat pada permukaan, dan inilah yang banyak dianggap ketika orang berhadapan dengan seni-seni yang dikategorikan “postmodern,” tentu orang akan menyangka bahwa sang perupa sekedar ingin meneguhkan bahwa arusutama tak bisa didefinisikan tanpa adanya aruspinggiran, bahwa Pancasila ataupun Islam moderat tak akan mungkin menetapkan identitasnya tanpa adanya “khilafah” ataupun Islam radikal.
Apakah doktrin harus meraba semata wilayah permukaan, tanpa berharap pada substansi, ketika orang berhadapan dengan karya-karya seni kontemporer dapat dipertanggungjawabkan, bahkan pun secara filosofis? Atau dengan kata lain, tak ada keseriusan dalam postmodernisme sebagaimana ketika orang mengucapkan inisial “IS” tanpa adanya intensi pada “Islam” atau bahkan “Islamic State”?
Pasca 2014, fakta membuktikan bahwa Indonesia tak pula dapat dilepaskan dari menggeliatnya fenomena Islam puritan dalam moral, Islam radikal dalam pemahaman, dan Islam struktural dalam politik, yang kerap dituduh sebagai pengoyak keberagaman yang merupakan karakter khas dari bangsa Indonesia. Secara hukum, pembubaran HTI dan FPI, juga terbongkarnya beberapa organisasi yang berinduk pada Islamic State (IS), adalah bukti bahwa diskursus tentang “khilafah,” “hijrah,” “syari’ah”—bahkan pun dalam bentuknya yang dianggap paling tak serius sebagaimana karya-karya seni—bukanlah semata “permainan.”
Secara filosofis, dan hal ini adalah tak terbantahkan, bahwa konsekuensi postmodernisme, dengan sikapnya yang amat sangat ramah terhadap perbedaan, terpaksa juga memberi ruang pada anasir-anasir yang memang pernah direpresi oleh modernisme, termasuk juga “radikalisme” yang tak urung akan membunuh postmodernisme itu sendiri. Maka, tak benar bahwa semangat “permainan” adalah karakteristik utama dari postmodernisme sebagaimana yang selama ini dikoarkoarkan, bahwa segala sesuatunya adalah yang sebenar-benarnya (Petaka Melankolia: Perihal Kebhinekaan, Kenusantaraan, Radikalisme dan Terorisme, Heru Harjo Hutomo, PT Nyala Masadepan Indonesia, Surakarta, 2021).
Beruntunglah bangsa Indonesia yang telah melewati fase demam “Islam” dan melankolia ke-1 tanpa kendala yang cukup berarti, yang sempat menghiasi dinamika kebangsaan dan kenegaraan yang ada. Dan fenomena demam “Islam” fase pertama itu adalah modal yang penting untuk menghadapi geliat demam “Islam” dan melankolia ke-2 yang memang sudah kentara.
Rumusnya ternyata sederhana, ketika pemerintah yang terpilih memegang semangat dan prinsip keberlanjutan, maka otomatis apa yang pernah menjadi “lalat” pada pemerintahan yang lalu akan kembali berkitar dan berupaya mengerumuni. Dan ketika pemerintahan yang lalu berhasil menyikapi “lalat-lalat” itu, tak terlalu berlebihan rasanya bahwa pemerintahan kini akan pula dapat menyikapinya.