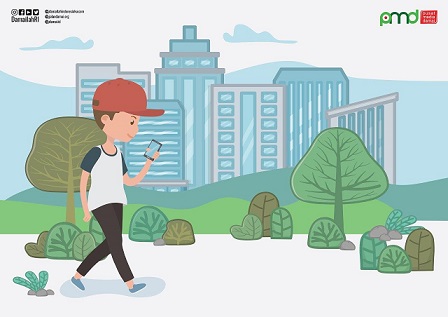“Agar kau pahami rahasia hidup, kusampaikan ihwal dengan segenap rahasianya. Mati sajalah kau jika tak punya jiwa. Jika kau punya, kau akan hidup kekal”. Itulah sepenggal sajak yang ditulis oleh penyair muslim Muhammad Iqbal. Dia dikenal dengan puisi-puisi sufistiknya serta pemikiran keislamannya yang bagi banyak kalangan dianggap dekonstruktif. Penggalan puisi Iqbal itu kiranya relevan dengan situasi sosial-kemanusiaan belakangan ini yang dipenuhi dengan kontradiksi.
Manusia hidup seolah tanpa jiwa. Kehidupan dinilai dari pencapaian materi. Kesuksesan dinilai dari hal-hal artifisial. Kian ke sini, manusia hidup tanpa mengindahkan nilai-nilai hukum, etika dan moralitas. Baik dan buruk, benar dan salah, legal dan ilegal tidak lagi memiliki garis batas yang jelas. Yang baik bisa dianggap buruk, yang salah dianggap benar, yang ilegal bisa negosiasikan agar menjadi legal. Parahnya lagi, dalam konteks beragama, batasan antara halal dan haram yang sebenarnya sudah jelas diatur dalam hukum fiqh pun acapkali bisa dipertukarkan dengan alasan kepentingan.
Tidak sedikit umat beragama yang hidup dengan berdasar standar ganda. Begitu mudah individu atau kelompok menuduh orang lain sesat atau kafir hanya karena memiliki pandangan yang berbeda. Namun, kita kerap menutup mata pada berbagai kemungkaran yang dilakukan oleh kelompoknya sendiri. Sederhananya, nilai etika, moralitas bahkan hukum telah dijungkirbalikkan oleh standar ganda yang sarat kepentingan.
Para filosof post-modern kerap menyebut situasi yang demikian itu sebagai hipermoralitas. Yakni sebuah situasi ketika moralitas mengalami krisis akibat dari ketiadaan batas antara baik dan buruk, benar dan salah bahkan legal dan ilegal. Wacana moralitas sendiri sebenarnya dibangun di atas fondasi relasi-relasi sosial. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan diskursus moralitas yang terjadi dalam tiga perkembangan.
Pertama, fase moralitas yang dibangun di atas fondasi ajaran agama. Di fase ini, ajaran dan hukum agama menjadi dasar penilaian apakah sesuatu dikatakan baik atau buruk, benar atau salah, serta halal atau haram. Fase ini terjadi ketika agama mendominasi nyaris seluruh aspek kehidupan manusia seperti terjadi di era Abad Pertengahan.
Kedua, fase ketika moralitas lebih didasarkan pada kepentingan politik, militer dan kekuasaan. Di masa ini, penilain baik dan buruk, benar dan salah serta legal dan illegal ditentukan dan diatur oleh konvensi atau kode-kode yang dibuat berdasarkan akal budi manusia sendiri dan semuanya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik atau kekuasaan.
Baca Juga :Menyoal Peran Agama(wan) dalam Krisis Lingkungan
Ketiga, fase ketika moralitas dipengaruhi oleh wacana ekonomi-politik. Yakni ketika penilaian moral lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik terutama kapitalisme. Di fase ini, apa yang baik adalah yang memberikan keuntungan pragmatis pada manusia. Sepanjang itu memberikan kebaikan dan keuntungan meski pun jangka pendek pada manusia, maka semua hal bisa dikategorikan sebagai kebaikan.
Inilah fase yang disebut sebagai era moralitas utilitaristik, yakni konsep moralitas yang mementingkan keuntungan bagi sebanyak mungkin manusia, meski itu akan merugikan sebagian kecil manusia lainnya. Contoh nyata moralitas utilitarianistik ini dapat dilihat dari bagaimana manusia memperlakukan alam. Eksploitasi alam secara besar-besaran dipandang baik, legal dan benar lantaran memberikan dampak positif bagi sebagian besar orang, meski hanya dalam jangka pendek.
Fakta bahwa eksploitasi atas alam dan lingkungan itu akan merugikan sebagian kecil manusia tidak akan menggugurkan nilai kebaikan yang dikandungnya. Konsep moralitas utilitarianistik ini banyak dikritik oleh kaum humanis yang berpandangan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk menentukan mana yang baik dan buruk, mana yang salah dan benar serta mana yang legal dan ilegal. Menafikan pendapat sebagian orang hanya karena jumlahnya yang minoritas adalah sebuah pengabaikan terhadap keseluruhan nilai-nilai humanisme yang sebenarnya menjadi ruh bagi era modern.
Masa-masa sekarang ini bisa dibilang sebagai fase moralitas yang ditentukan oleh kepentingan ekonomi-politik dimana semua penilaian baik dan buruk dilihat dari sejauh mana hal itu memberikan dampak positif bagi sebagian besar manusia. Ini artinya, tidak ada lagi pegangan baik penilaian baik dan buruk karena semua dinilai dari kepentingan-kepentingan kelompok mayoritas yang berkuasa.
Penggundulan hutan, bahkan pembunuhan massal bisa saja dianggap baik jika itu disetujui oleh kelompok mayoritas arus-utama. Situasi yang demikian ini tidak pelak membuat manusia berada di dalam kondisi yang centang-peranang, serba tidak pasti, tumpang-tindih dan silang sengkarut. Julia Kristeva, pemikir postmodern perempuan mengistilahkannya sebagai abjection, yakni situasi individua tau masyarakat yang berada di dasar jurang moralitas paling rendah.
Moralitas berada di titik paling nadir lantaran ketiadaan batas dan rujukan yang jalas dimana manusia bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah serta legal dan ilegal. Moralitas mengalami ambigu dan turbulensi. Individu atau kelompok bisa dengan bangganya memamerkan perbuatan melanggar etika dan hukum lantaran merasa diri paling berkuasa.
Fase abjeksi moralitas ini menandai kegagalan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keistimewaan manusia yang memiliki akal dan rasio untuk berpikir justru kerap menjadikan manusia bertindak sekehendak hati dan sewenang-wenang. Atas nama kepentingan ekonomi, politik dan agama manusia kerap tega mengeksploitasi alam dan sesama manusia.
Kerusakan ekologis terjadi di mana-mana. Keadilan sosial semakin merajalela. Nasib peradaban manusia kini berada di ujung tanduk. Ancaman bencana akibat kerusakan alam sudah ada di depan mata, bersanding dengan potensi perang nuklir yang bisa meledak kapan saja. Ketika perjalanan sejarah manusia sampai pada fase kritis-nihilistik seperti kita alami saat ini, kembali pada ajaran agama kiranya adalah jawaban atas situasi tersebut.
Namun, agama seperti apakah yang mampu menyediakan solusi? Apakah agama seperti tampak dalam gerakan-gerakan ideologis-politis seperti belakangan ini mengemuka? Tentu saja tidak! Kita harus kembali pada agama yang lebih mengedepankan aspek spiritualitas ketimbang aspek simbolik. Spiritualitas akan berfungsi mengendalikan hasrat manusia pada kekuasaan politik, ekonomi dan arogansi keagamaan.
Alvin Toffler, pemikir futuristik pernah berujar bahwa mesin-mesin hasrat berupa kapitalisme ekonomi, liberalisme politik dan fundamentalisme agama yang telah menimbulkan banyak kerusakan itu hanya dapat dikendalikan oleh spiritualitas. Ketertundukan manusia pada kekuatan spiritual akan membuatnya sadar bahwa kekayaan ekonomi, kekuasaan politik dan simbolisme agama hanyalah hal-hal yang semu. Kesejatian hidup adalah ketika manusia mampu menjadi penjaga alam dan lingkungans serta menjadi mitra bagi sesamanya.
Menumbuhkan spiritualitas di tengah praktik keberagamaan yang kering kerontang akan makna dan sebaliknya subur oleh nalar simbolisme tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan dekonstruksi cara pandang dan praktik keagamaan yang mengarahkan umat beragama untuk tidak hanya berhenti pada wilayah terluar (eksoterik) agama melainkan menyelami area terdalam (esoterik) agama. Di wilayah esoterik agama itulah manusia dimungkinkan untuk menemukan ajaran tentang cinta-kasih, welas asih dan kebaikan yang bisa dijadikan fondasi dan sumber hukum, etika dan moralitas.