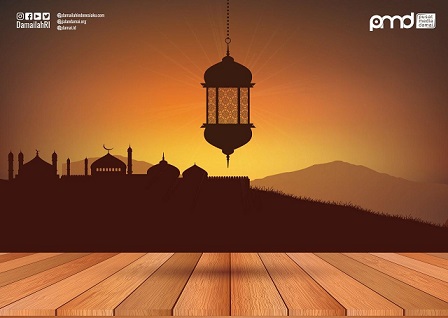Beberapa waktu lalu (3/3/2020), massa yang menamakan diri “Aliansi Masyarakat Jogja” berdemonstrasi memperingati 96 tahun berakhirnya khilafah. Peringatan itu merujuk pada berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani pada 3 Maret 1924. Demonstrasi itu diwarnai poster berisi bermacam slogan agitatif yang menghebohkan publik.
Belakangan diketahui massa demo berasal dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. Kampus dan mahasiswa yang selama ini digadang menjadi mercusuar intelektualitas dan agen transformasi sosial nyatanya justru terjebak dalam romantisme sejarah masa lalu. Sejumlah survei menyebutkan, gagasan khilafah berkembang di kalangan muslim kelas menengah perkotaan berletar belakang pendidikan tinggi dan tingkat ekonomi mapan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan, mengapa kelas menengah berpendidikan tinggi dan berekonomi mapan yang adaptif pada modernisme justru gandrung pada ajakan kembali ke masa lalu yang mewujud pada gerakan khilafah?
Secara sosiologis, kelompok kelas menengah ialah kelas sosial yang paling diuntungkan dengan adanya modernitas. Mereka memiliki akses pada pendidikan tinggi, akrab dengan teknologi modern dan sebagian besarnya bekerja di sektor formal. Meski demikian, cara pandang kelompok kelas menengah, terutama dalam hal keagamaan, tampaknya tidak selalu moderat. Di titik tertentu, kelompok muslim kelas menengah justru menjadi penyumbang paling besar bagi fenomena konservatisme agama di Indonesia yang terjadi selama satu dekade belakangan ini.
Konservatisme Kelas Menengah
Demonstrasi peringatan 96 tahun keruntuhan kekhilafahan Turki Usmani itu membuktikan untuk ke sekian kalinya bahwa ideologi khilafah masih tumbuh subur utamanya di kalangan muslim kelas menengah, meski organisasi induknya telah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Romantisme kejayaan era khilafah di masa lalu yang dikemas menjadi retorika politik itu terbukti laku keras di kelompok masyarakat yang tengah gamang dalam menghadapi modernisme.
Baca Juga : Bencana Corona Dan Ekologi Pancasila
Di satu sisi, muslim kelas menengah-perkotaan, dikenal adaptif pada modernisme. Mereka adaptif pada berbagai produk teknologi modern yang lahir dari rahim peradaban Barat yang sekuleristik. Namun di sisi lain, mereka juga merasa insecure alias khawatir modernisme berdampak pada lunturnya kemurnian iman Islam yang mereka anut. Di saat yang sama, mereka juga menyaksikan sendiri bagaimana modernisme yang digadang-gadang sebagai proyek pencerahan (enlightenment) yang bertumpu pada nilai kemanusiaan (humanism) justru melahirkan beragam krisis sosial-kemanusiaan.
Beberapa dekade belakangan ini, kita menyaksikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Barat berhasil mengantarkan manusia pada capaian di berbagai bidang. Berbagai temuan teknologi termutakhir telah menuntun manusia pada satu kondisi peradaban dunia yang lebih maju. Mobilitas manusia tidak lagi terbatas dengan kecanggihan alat transportasi. Relasi sosial pun tidak lagi mengenal sekat lantaran adanya revolusi di bidang teknologi dan komunikasi. Belum lagi menyebut capaian modernisme di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.
Namun, puncak peradaban modern justru melahirkan berbagai krisis sosial-kemanusiaan. ekonomi kapitalisme yang digadang mampu mensejahterakan umat manusia terjebak pada sistem perdagangan bebas yang oligopolistik dan monopolistik. Bertumpuknya modal di satu kelompok memperlebar kesenjangan ekonomi. Saat ini, sebagian besar aset ekonomis dunia dikendalikan golongan elite super kaya yang jumlahnya hanya satu persen dari total populasi dunia. Sisanya adalah kelas menengah-pekerja yang harus bekerja mati-matian untuk bisa hidup layak.
Ekonomi kapitalisme juga telah melahirkan praktik eksploitasi alam yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup. Perubahan iklim sebagai konsekuensi pemanasan global kian tidak terkendali. Industrialisme sebagai anak kandung kapitalisme membuat manusia abai pada kelestarian alam dan berakibat pada rusaknya planet bumi. Krisis ekonomi dan ekologi itu kian diperparah dengan degradasi moral-sosial masyarakat. Masyarakat modern diidentikkan sebagai masyarakat individualistis dan pragmatis. Universalitas hak asasi manusia yang diterjemahkan secara dangkal sebagai kebebasan individu melatari munculnya penyimpangan sosial, seperti seks bebas, penggunaan narkoba, kriminalitas dan sebagainya.
Di tengah paradoks modernisme inilah, wacana romantisme khalifah tumbuh subur di kalangan Muslim menengah-perkotaan. Kelompok ini, cenderung percaya anggapan bahwa modernisme Barat adalah ancaman bagi dunia Islam dan sumber malapetaka ekonomi dan ekologi. Mereka juga meyakini doktrin kaum islamis yang meganggap khilafah sebagai solusi mengatasi segala persoalan tersebut.
Islam Progresif
Para intelektual muslim sebenarnya tidak tinggal diam menyikapi menguatnya sentimen romantisme khilafah tersebut. Sebagian pemikir Islam menawarkan gagasan pemisahan antara agama dan politik. Tawaran ini mengadopsi paham sekulerisme yang berkembang di Eropa di awal era Pencerahan. Sekulerisme Islam ini dikembangkan oleh Ali Abdur Raziq (Mesir), Abdullah Ahmed an Naim (Tunisia), Nurcholis Madjid (Indonesia) dan sejumlah nama lainnya. Mereka kerap digolongkan ke dalam gerbong pemikir Islam liberal. Yakni pemikir yang berusaha mengadopsi sepenuhnya modernisme Barat tanpa melakukan kritik terlebih dahulu.
Alih-alih menyelesaikan problem di dunia Islam, Islam liberal justru menimbulkan problem baru di kalangan muslim. Pola adopsi pemikiran modern ala Barat ke dunia Islam secara literal melahirkan tidak hanya kontroversi namun juga sejumlah “penyimpangan”. Alhasil, Islam liberal pun lebih banyak menuai kontroversi ketimbang mampu membongkar kejumudan berpikir di kalangan umat Islam.
Belakangan, muncul tawaran pemikiran yang berupaya melampaui Islam liberal dan Islam fundamentalis sekaligus. Kluster pemikiran ini populer disebut Islam progresif. Tokohnya antara lain Omid Safi (Turki), Farish Ahmad Noor (Malaysia), Salahudin Jursyi (Tunisia) Ebrahim Moosa (Afrika Selatan) dan nama-nama lainnya. Islam progresif dicirikan dengan sikap adaptif sekaligus kritisnya pada modernisme maupun tradisionalisme Islam.
Islam progresif tidak mau terjebak pada pengagungan modernisme sebagaimana Islam liberal, namun juga tidak mau terbelenggu romantisme seperti kaum fundamentalis-ortodoks. Islam progresif berupaya mensintesiskan modernisme Barat dan Islam. Maka, tidak mengherankan jika para pemikir Islam progresif sangat kritis pada kelompok modernis-liberal dengan kaum fundamentalis-ortodoks sekaligus.
Bagi Islam progresif, keduanya tidak memberi solusi apa pun, alih-alih menambah persoalan di dunia Islam. Dalam konteks politik, Islam progresif mengajak umat muslim untuk tidak hanyut pada romatisme khilafah. Namun, Islam progresif juga tidak lantas mengadopsi begitu saja sistem demokrasi liberal ala Barat.
Para pemikir Islam progresif menawarkan demokrasi Islam yang memadukan sistem demokrasi Barat dengan konsep musyawarah ala Islam. Demokrasi Islam inilah yang menurut Islam progresif relevan dikembangkan di masyarakat muslim modern-kontemporer. Demokrasi Islam ialah demokrasi yang menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan semua warganegara, tanpa membedakan kelas sosial dan identitas pribadinya (jenis kelamin, warna kulit, etnis, ras, suku, agama dan sejenisnya). Tawaran para pemikir Islam progresif ini agaknya patut kita tindaklanjuti ke dalam gerakan nyata terkait demokratisasi dunia Islam. Demokratisasi dunia Islam idealnya dipahami sebagai sebuah upaya menciptakan rezim pemerintahan di negara-negara muslim yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan publik, alih-alih hanya berkutat pada aspek kekuasaan semata. Jika dunia Islam berhasil melahirkan rezim-rezim pemerintahan yang demokratis dan adil, dengan sendirinya sindrom romantisme khilafah yang menjangkiti sebagian umat Islam akan hilang dengan sendirinya.